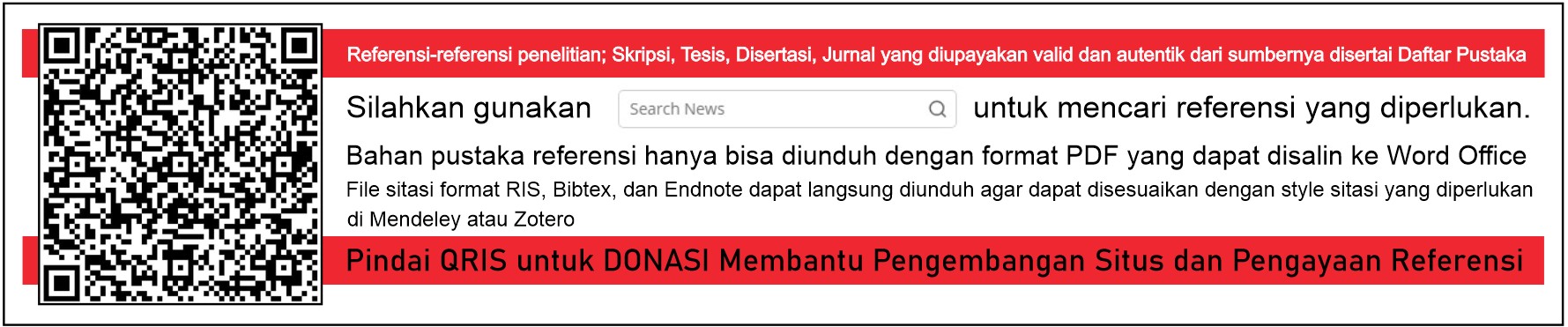Reformasi kepolisian merupakan isu krusial yang mendapat perhatian luas dalam diskursus kebijakan publik, hak asasi manusia, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dalam satu dekade terakhir, berbagai negara menghadapi tantangan dalam merombak struktur, budaya, dan praktik kepolisian agar lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu ini, literatur ilmiah mengenai reformasi kepolisian pun berkembang pesat, mencerminkan dinamika global serta variasi pendekatan di berbagai konteks nasional.
Untuk memahami perkembangan dan arah penelitian terkait reformasi kepolisian secara global, studi ini melakukan analisis bibliometrik terhadap publikasi ilmiah yang tersedia di basis data Scopus dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yakni dari tahun 2015 hingga 2025. Dari hasil penelusuran awal, diperoleh sebanyak 200 dokumen jurnal yang membahas topik ini. Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut diseleksi berdasarkan relevansi terhadap tema reformasi kepolisian dan tingkat pengaruhnya yang diukur melalui jumlah sitasi. Hasil seleksi ini menghasilkan 61 dokumen yang dijadikan dasar dalam analisis lebih lanjut.
Melalui bibliometrik ini, dapat teridentifikasi tren penelitian, penulis dan institusi paling produktif, kolaborasi antarnegara, serta topik-topik yang paling sering dibahas dalam konteks reformasi kepolisian. Dengan demikian, tidak hanya menyajikan pemetaan terhadap lanskap penelitian yang ada, tetapi juga memberikan gambaran mengenai arah perkembangan ilmu pengetahuan dan potensi kesenjangan riset yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut.
Network Visualization Reformasi Kepolisian
Analisis bibliometrik terhadap 61 dokumen terpilih mengungkap bahwa tema utama dalam penelitian reformasi kepolisian selama satu dekade terakhir secara konsisten berpusat pada tiga isu kunci: police reform (113 kemunculan), police accountability (95), dan sejumlah isu turunan lainnya seperti community policing (22), civilian oversight (18), racial disparities (166), serta public opinion (158). Frekuensi tinggi istilah-istilah ini dalam judul, abstrak, dan kata kunci menunjukkan fokus yang kuat terhadap upaya restrukturisasi institusional, peningkatan akuntabilitas, serta keterkaitan antara kepolisian dan masyarakat sipil.
Secara lebih spesifik, istilah police reform muncul sebanyak 35 kali sebagai kata kunci, diikuti oleh police accountability (14), Black Lives Matter (5), public opinion (5), dan community policing (3). Meskipun community policing memiliki frekuensi lebih rendah sebagai kata kunci, posisinya tetap penting dalam peta jaringan karena keterhubungannya dengan tema utama seperti reformasi struktural dan persepsi publik terhadap kepolisian.
Perkembangan temporal dalam literatur juga menunjukkan pergeseran fokus penelitian, terutama pada periode 2023–2024. Isu-isu baru yang mulai mendapat sorotan meliputi organizational resilience (87), policing attitudes (131), racial perception (171), civil society involvement (17), dan partisanship and policing (92). Pergeseran ini menandakan peralihan dari fokus yang sebelumnya lebih terpusat pada aspek formal seperti akuntabilitas hukum dan pengawasan sipil, menuju isu-isu yang lebih kompleks dan multidimensi yang mencakup dinamika sosial-politik, persepsi masyarakat, dan ketahanan kelembagaan.
Berdasarkan analisis keterhubungan dalam visualisasi jejaring topik (RefPol Net), tampak bahwa police reform menjadi simpul sentral (central node) yang menghubungkan hampir seluruh tema utama. Node ini terkoneksi langsung dengan berbagai isu krusial seperti community policing, police accountability, racial disparities, public opinion, gender representation, misconduct, hingga systemic racism (dengan 190 koneksi), menjadikannya pusat gravitasi dari keseluruhan jaringan literatur.
Jejaring ini membentuk beberapa cluster tematik yang menggambarkan fokus-fokus penelitian yang saling berelasi:
- Cluster hukum dan institusi, yang mencakup tema-tema seperti police accountability, consent decrees, Department of Justice, dan civilian oversight.
- Cluster sosial-politik dan opini publik, dengan istilah kunci seperti Black Lives Matter, racial disparities, public opinion, dan protest policing.
- Cluster gender dan representasi, yang membahas topik gender equality, women in policing, dan gender-based violence.
- Cluster internasional dan komparatif, yang menyertakan studi kasus dari berbagai negara seperti Kenya, Lagos, Trinidad and Tobago, Sweden, dan Slovenia, menunjukkan bahwa isu reformasi kepolisian juga menjadi perhatian dalam konteks global dan lintas budaya.
Peta jaringan (network map) yang dihasilkan dari visualisasi bibliometrik ini secara jelas menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak hanya menjadi tema dominan, tetapi juga hub utama yang mengintegrasikan berbagai bidang kajian, mulai dari hukum, sosial-politik, hingga kelembagaan dan perspektif global. Temuan ini menunjukkan bahwa wacana reformasi kepolisian semakin berkembang menjadi ruang interdisipliner yang mencerminkan kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian modern.
Overlay Visualization Reformasi Kepolisian
Visualisasi overlay dalam analisis bibliometrik ini memberikan dimensi temporal yang memperkaya pemahaman terhadap arah dan evolusi penelitian reformasi kepolisian selama satu dekade terakhir. Dengan menggunakan warna sebagai indikator rata-rata tahun publikasi, overlay map memperlihatkan bagaimana fokus penelitian mengalami transisi yang signifikan dari waktu ke waktu, dari respons terhadap peristiwa aktual menuju pembahasan isu-isu struktural dan sistemik yang lebih luas.
Pada periode 2020–2021, literatur didominasi oleh tema-tema yang sangat dipengaruhi oleh peristiwa besar, seperti pembunuhan George Floyd dan gerakan Black Lives Matter. Istilah seperti police accountability, police misconduct, defund the police, dan Black Lives Matter sendiri muncul sebagai kata kunci utama, menunjukkan bahwa fokus penelitian saat itu banyak terpusat pada respons terhadap insiden kekerasan polisi, krisis legitimasi institusional, dan tuntutan reformasi mendesak dari masyarakat sipil.
Memasuki tahun 2022, arah penelitian mulai mengalami pergeseran. Topik-topik baru seperti gender equity, systemic racism, dan marijuana enforcement mulai mendapat perhatian yang lebih besar. Pergeseran ini menandakan transisi dari fokus pada kejadian-kejadian spesifik menuju analisis terhadap struktur ketidakadilan yang lebih mendalam, termasuk isu representasi dan ketimpangan dalam penegakan hukum yang selama ini kurang mendapat sorotan.
Pada 2023–2024, tren ini berlanjut dengan munculnya tema-tema baru seperti organizational resilience, policing attitudes, civil society involvement, racial perception, dan protest policing. Fokus penelitian bergeser dari insiden dan peristiwa ke aspek yang lebih konseptual dan sistemik, mencakup studi tentang ketahanan organisasi kepolisian, persepsi masyarakat terhadap polisi, serta peran masyarakat sipil dalam proses reformasi. Pergeseran ini mencerminkan kedewasaan wacana ilmiah yang tidak lagi hanya reaktif terhadap peristiwa, tetapi mulai mengkaji fondasi-fondasi sosial, politik, dan budaya yang membentuk dinamika kepolisian dalam jangka panjang.
Dengan demikian, overlay visualization menegaskan adanya transisi epistemologis dalam kajian reformasi kepolisian: dari fokus reaktif terhadap insiden menuju pendekatan yang lebih struktural, partisipatif, dan bahkan transnasional. Hal ini menunjukkan bahwa studi-studi mutakhir semakin menempatkan reformasi kepolisian dalam kerangka besar perubahan kelembagaan, keadilan sosial, dan demokratisasi hubungan antara negara dan warga.
Density Visualization Reformasi Kepolisian
Visualisasi kepadatan atau density visualization dalam analisis bibliometrik ini berfungsi untuk mengidentifikasi topik-topik yang menjadi pusat perhatian dalam literatur reformasi kepolisian. Peta densitas secara visual menggambarkan area-area dengan konsentrasi istilah yang tinggi, yang menunjukkan frekuensi kemunculan sekaligus intensitas perhatian ilmiah terhadap tema tertentu.
Dari hasil pemetaan, terlihat bahwa area dengan kepadatan tertinggi terletak pada lima istilah utama: police reform (113), police accountability (95), public opinion (158), racial disparities (166), dan community policing (22). Kelima istilah ini muncul sebagai inti konseptual (core concepts) dalam kajian reformasi kepolisian. Tingginya konsentrasi istilah-istilah ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dalam satu dekade terakhir masih berakar pada perdebatan mengenai pertanggungjawaban lembaga kepolisian, persepsi publik, ketimpangan rasial dalam penegakan hukum, serta pendekatan berbasis komunitas.
Sebaliknya, istilah-istilah seperti organizational resilience (87), partisanship and policing (92), serta racial perception berada di area dengan kepadatan rendah atau di pinggiran peta. Meskipun frekuensinya masih relatif kecil dibandingkan tema utama, keberadaan istilah-istilah ini menunjukkan munculnya frontier penelitian baru. Isu-isu tersebut mencerminkan perluasan fokus akademik ke arah analisis struktural, dinamika kelembagaan, dan pengaruh politik dalam praktik kepolisian.
Dengan demikian, density map berfungsi tidak hanya untuk mengidentifikasi pusat gravitasi dalam literatur yang sudah mapan, tetapi juga menyoroti ruang-ruang kosong (research gaps) yang mulai diisi oleh agenda-agenda riset kontemporer. Lima tema dengan kepadatan tertinggi dapat dipahami sebagai kerangka konseptual dominan dalam studi reformasi kepolisian, sementara tema-tema dengan densitas rendah menandai potensi arah pengembangan penelitian masa depan, terutama dalam konteks global yang terus berubah dan menuntut pendekatan lintasdisipliner yang lebih holistik.
Celah PenelitianReformasi Kepolisian
Meskipun literatur mengenai reformasi kepolisian mengalami perkembangan yang pesat dalam satu dekade terakhir, analisis bibliometrik ini mengungkap adanya sejumlah kesenjangan penelitian yang masih terbuka lebar untuk dieksplorasi. Celah-celah ini mencakup aspek temporal, konseptual, metodologis, hingga konteks geografis, yang secara kolektif menunjukkan bahwa kajian reformasi kepolisian masih dalam proses pertumbuhan menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif.
1. Kesenjangan Temporal
Sebagian besar publikasi yang muncul pada periode 2020–2021 sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian besar yang memicu gelombang protes publik, seperti pembunuhan George Floyd dan gerakan Black Lives Matter. Fokus penelitian pada masa ini banyak berkutat pada isu police accountability, misconduct, serta wacana defund the police. Sementara itu, tema-tema yang muncul belakangan seperti organizational resilience, partisanship and policing, serta civil society involvement, yang mulai mendapatkan perhatian pada 2023–2024, masih tergolong jarang dikaji secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya ruang signifikan untuk pengembangan riset di bidang-bidang baru tersebut, khususnya yang berkaitan dengan dinamika kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam reformasi institusi kepolisian.
2. Kesenjangan Konseptual
Dari sisi konseptual, literatur yang ada masih terpusat pada isu akuntabilitas formal dan pengawasan hukum terhadap institusi kepolisian. Meskipun penting, pendekatan ini seringkali belum cukup untuk menjelaskan kompleksitas hubungan antara polisi dan masyarakat dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Kajian yang menghubungkan reformasi kepolisian dengan faktor-faktor sosial-politik, seperti partisanship, opini publik, representasi gender, dan persepsi rasial, masih terbatas. Selain itu, keterkaitan antara reformasi kepolisian dan kerangka tata kelola yang lebih luas, seperti good governance, demokratisasi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara, belum banyak dieksplorasi secara konseptual maupun empiris.
3. Kesenjangan Metodologis
Dari segi metodologi, mayoritas studi yang ada cenderung menggunakan pendekatan normatif, kualitatif, atau studi kasus, terutama yang merujuk pada kejadian-kejadian spesifik di Amerika Serikat seperti insiden di Ferguson, Minneapolis, atau New York. Penelitian dengan desain kuantitatif komparatif lintas negara, analisis longitudinal, atau pendekatan big data masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak studi yang menerapkan pendekatan mixed-methods, yang menggabungkan analisis jejaring (network analysis), survei opini publik, serta evaluasi kebijakan secara sistematis. Padahal, pendekatan metodologis semacam ini berpotensi memberikan gambaran yang lebih utuh dan kontekstual terhadap kompleksitas reformasi kepolisian.
4. Kesenjangan Konteks Lokal dan Global
Literatur yang tersedia saat ini masih didominasi oleh studi-studi dari Amerika Serikat dan Eropa Barat, sementara konteks negara berkembang atau Global South, seperti Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, dan Amerika Latin, masih jarang disentuh. Padahal, negara-negara di wilayah ini memiliki tantangan dan dinamika kepolisian yang unik, terutama terkait dengan community policing, peran masyarakat sipil, serta legitimasi institusi kepolisian dalam konteks pasca-otoritarian atau negara dengan tata kelola lemah. Minimnya studi dari wilayah ini menciptakan kesenjangan representasi dalam literatur global, sekaligus membuka peluang untuk penelitian yang lebih kontekstual dan inklusif.
Novelty Kebaharuan Reformasi Kepolisian
Berdasarkan analisis bibliometrik terhadap tren dan sebaran topik dalam literatur reformasi kepolisian selama sepuluh tahun terakhir, terlihat bahwa meskipun telah terjadi ekspansi topik, masih banyak ruang kebaruan yang dapat dikembangkan oleh peneliti, baik dari sisi teori, pendekatan metodologis, maupun konteks empiris. Kebaruan ini penting tidak hanya untuk mengisi celah penelitian yang ada, tetapi juga untuk memperluas cakrawala konseptual reformasi kepolisian agar lebih sesuai dengan kompleksitas sosial-politik kontemporer.
1. Integrasi Dimensi Sosial-Politik dalam Reformasi Kepolisian
Salah satu arah kebaruan yang signifikan adalah mengintegrasikan dimensi sosial-politik secara lebih eksplisit ke dalam studi reformasi kepolisian. Meskipun akuntabilitas hukum dan oversight institusional telah banyak dibahas, belum banyak studi yang secara sistematis mengaitkan reformasi kepolisian dengan partisanship politik, interferensi politik dalam kebijakan kepolisian, serta dinamika opini publik. Kajian mengenai bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi legitimasi kepolisian di mata masyarakat dapat menjadi kontribusi teoritik dan empiris yang signifikan, terutama di tengah polarisasi politik yang meningkat di berbagai negara.
2. Peran Civil Society dan Organisasi Non-Pemerintah
Topik mengenai civil society involvement mulai muncul dalam beberapa literatur terbaru, namun masih dalam tahap awal dan terbatas pada konteks tertentu. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi peran organisasi masyarakat sipil, NGO, kelompok advokasi, dan media independen dalam mendorong akuntabilitas, transparansi, serta pembentukan agenda reformasi. Pendekatan ini membuka ruang kolaboratif antara studi kebijakan publik, sosiologi politik, dan tata kelola demokratis.
3. Gender, Representasi, dan Diversity
Aspek gender dan keragaman representasi dalam institusi kepolisian merupakan bidang yang masih relatif kurang dieksplorasi dalam literatur utama. Padahal, isu seperti gender equity, peran perempuan dalam kepolisian, hingga fenomena glass cliff, di mana perempuan sering ditempatkan dalam posisi kepemimpinan saat krisis, berpotensi menjadi titik masuk penting untuk memahami resistensi dan keberhasilan reformasi. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi keamanan, gender studies, dan governance dapat memperkaya diskursus reformasi dengan perspektif yang lebih inklusif.
4. Resilience dan Transformasi Organisasi
Topik seperti organizational resilience, legitimacy, dan transformasi kelembagaan semakin relevan dalam konteks dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian sosial-politik. Namun, istilah-istilah ini masih berada di pinggiran peta densitas literatur. Penelitian mendalam mengenai bagaimana institusi kepolisian beradaptasi terhadap krisis, mengelola perubahan, serta membangun ulang legitimasi publik akan sangat penting bagi perancangan reformasi jangka panjang. Ini juga relevan dengan pendekatan governance adaptif dalam studi kelembagaan kontemporer.
5. Komparasi Global South dan Global North
Kebaruan penting lainnya adalah mengembangkan kajian komparatif lintas wilayah antara negara-negara Global South dan Global North. Konteks seperti Kenya, Nigeria, Trinidad and Tobago, atau negara-negara di Asia Tenggara, seringkali menunjukkan model community policing dan reformasi yang berbasis nilai-nilai lokal, yang sangat berbeda dari pendekatan institusional di Amerika Serikat atau Eropa. Studi komparatif semacam ini tidak hanya mengatasi kesenjangan representasi dalam literatur, tetapi juga memberikan wawasan mengenai keberagaman model reformasi yang kontekstual dan berbasis pengalaman lokal.
Dalam konteks Indonesia, peluang untuk mengembangkan kebaruan (novelty) dalam studi reformasi kepolisian sangat terbuka lebar, terutama dengan mengadaptasi dan mengontekstualisasikan tren global ke dalam dinamika lokal. Salah satu arah kebaruan yang penting adalah integrasi dimensi sosial-politik dalam analisis reformasi kepolisian. Selama ini, kajian di Indonesia masih dominan membahas aspek kelembagaan dan normatif, sementara hubungan antara reformasi kepolisian dengan partisanship politik, opini publik, dan intervensi politik belum banyak dieksplorasi. Padahal, dalam konteks demokrasi elektoral yang kompleks seperti Indonesia, dinamika politik sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan kinerja institusi kepolisian. Kebaruan lain yang potensial adalah eksplorasi peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam mendorong akuntabilitas serta pengawasan institusional. Walaupun aktor-aktor ini kerap terlibat dalam advokasi dan kontrol sosial terhadap kepolisian, kontribusi mereka belum banyak menjadi fokus studi akademik secara sistematis.
Selain itu, isu representasi dan keberagaman dalam tubuh Polri juga menawarkan ruang pengembangan riset yang signifikan. Belum banyak studi yang mengkaji secara mendalam peran perempuan dalam kepolisian Indonesia, termasuk dinamika gender di tingkat struktural dan operasional, serta kaitannya dengan efektivitas pelayanan publik dan penerimaan masyarakat. Tema kebaruan lainnya adalah kajian mengenai organizational resilience dan transformasi kelembagaan Polri dalam menghadapi krisis sosial-politik, seperti pandemi, penurunan kepercayaan publik, atau konflik sosial. Studi semacam ini penting untuk memahami bagaimana institusi kepolisian beradaptasi, mempertahankan legitimasi, serta mengelola tekanan terhadap perubahan. Terakhir, pendekatan komparatif antara Indonesia dan negara-negara Global South seperti Kenya, Filipina, atau Brasil dapat membuka perspektif baru dalam memahami model community policing, reformasi berbasis nilai lokal, serta tantangan kelembagaan yang serupa dalam konteks negara berkembang. Melalui arah-arah kebaruan ini, riset reformasi kepolisian di Indonesia tidak hanya dapat mengisi celah dalam literatur nasional, tetapi juga berkontribusi secara lebih luas pada wacana internasional mengenai tata kelola keamanan yang demokratis dan responsif.
file pdf download disini