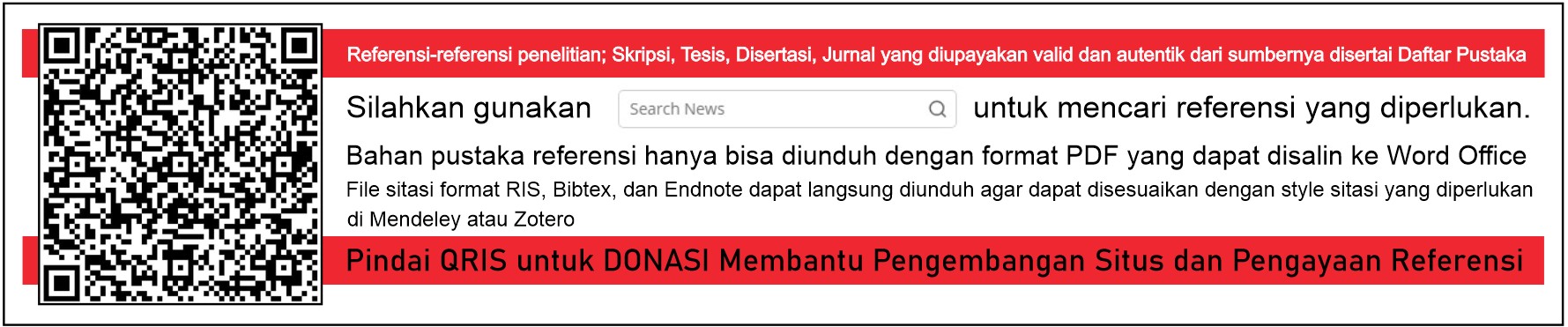Fenomena politik identitas semakin menempati posisi sentral dalam perdebatan akademik dan dinamika politik global, terutama dalam konteks meningkatnya polarisasi ideologis, populisme, serta kontestasi makna identitas dalam ruang publik. Dalam dekade terakhir, politik identitas tidak lagi terbatas pada isu agama atau etnis, tetapi telah berkembang ke dalam ranah gender, orientasi seksual, kelas sosial, bahkan ekspresi digital dan budaya populer. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik identitas bukan semata-mata gejala lokal, melainkan bagian dari transformasi politik global yang kompleks dan multidimensi.
Untuk memahami bagaimana perkembangan kajian akademik terhadap isu ini berlangsung secara global, penelitian ini melakukan analisis bibliometrik terhadap publikasi ilmiah bertema identity politics dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Basis data yang digunakan adalah Scopus, yang merupakan salah satu database indeksasi akademik terbesar dan paling kredibel secara internasional. Dari proses pencarian awal dengan kata kunci “identity politics”, ditemukan 200 dokumen jurnal ilmiah. Selanjutnya, dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria relevansi tematik dan jumlah sitasi, guna memastikan kualitas dan signifikansi karya yang dianalisis. Dari proses tersebut diperoleh 125 dokumen terpilih yang menjadi dasar kajian bibliometrik ini.
Network Visualization Politik Identitas
Visualisasi jaringan (network visualization) dalam kajian politik identitas memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola keterkaitan antar-topik yang berkembang dalam literatur. Istilah politik identitas muncul sebagai node sentral atau simpul utama dalam peta jaringan, yang menjadi titik penghubung bagi berbagai tema besar seperti agama, etnisitas, demokrasi, populisme, konflik, nasionalisme, hingga pemilihan kepala daerah (pilkada). Posisi sentral ini menandakan bahwa politik identitas bukan hanya sebuah topik mandiri, melainkan juga kerangka payung yang menaungi berbagai diskursus dan praktik politik kontemporer.
Dari peta jaringan tersebut terbentuk beberapa klaster tematik yang mencerminkan arah pembahasan yang spesifik namun saling berkelindan. Pertama, klaster agama dan politik mencakup istilah-istilah seperti Islam politik, politik keagamaan, konservatisme, dan gerakan sosial berbasis agama. Klaster ini menyoroti peran signifikan agama dalam membentuk identitas politik kolektif, serta keterlibatannya dalam mobilisasi sosial dan wacana moralitas publik. Kedua, klaster etnisitas dan konflik terdiri dari topik seperti politik etnis, konflik horizontal, pluralisme, dan minoritas, yang menggambarkan bagaimana identitas etnis menjadi sumber sekaligus arena konflik dalam masyarakat multikultural, khususnya dalam konteks distribusi kekuasaan dan pengakuan politik.
Klaster ketiga adalah demokrasi dan elektoral, yang berisi istilah-istilah seperti partisipasi politik, pilkada, pemilu, politik elektoral, dan populisme. Dalam klaster ini terlihat bahwa politik identitas juga memainkan peran penting dalam dinamika pemilu dan kontestasi kekuasaan, baik melalui simbolisme identitas maupun strategi politik berbasis segmentasi sosial. Terakhir, terdapat klaster wacana global, yang meliputi tema-tema seperti nasionalisme, globalisasi, identitas budaya, dan politik transnasional. Klaster ini memperlihatkan bagaimana politik identitas tidak hanya beroperasi dalam kerangka lokal atau nasional, tetapi juga menjadi bagian dari pertarungan identitas dalam konteks global yang lebih luas.
Secara keseluruhan, network visualization ini menegaskan bahwa politik identitas merupakan simpul analitis yang menjembatani berbagai dimensi sosial-politik, dari yang berbasis agama dan etnis, hingga yang berhubungan dengan institusi demokrasi dan arus globalisasi. Hubungan-hubungan ini menunjukkan bahwa kajian politik identitas tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas struktur sosial dan dinamika politik yang membentuk masyarakat kontemporer, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.
Overlay Visualization Politik Identitas
Visualisasi overlay (overlay visualization) memberikan gambaran temporal mengenai dinamika perkembangan kajian politik identitas berdasarkan tahun publikasi rata-rata dari literatur yang dianalisis. Peta ini secara kronologis menunjukkan bagaimana fokus dan orientasi riset mengalami pergeseran seiring waktu, mengikuti konteks sosial-politik yang terus berubah. Pada periode awal, yakni antara 2015 hingga 2018, literatur cenderung terpusat pada pembahasan mengenai politik identitas berbasis agama dan etnis, khususnya dalam konteks konflik sosial dan kontestasi elektoral, seperti pilkada dan pemilu daerah. Studi pada masa ini banyak menyoroti bagaimana simbol-simbol keagamaan dan etnis digunakan sebagai alat mobilisasi politik dalam arena lokal, serta potensi fragmentasi sosial yang ditimbulkannya.
Memasuki periode 2019 hingga 2021, terjadi perluasan topik kajian ke arah isu-isu yang lebih kompleks dan kontemporer, seperti populisme, politik elektoral berbasis identitas, demokrasi digital, serta mobilisasi massa melalui media daring. Perkembangan ini mencerminkan respons akademik terhadap dinamika politik nasional maupun global, di mana identitas politik tidak lagi bersifat lokalistik, melainkan mulai dikaitkan dengan fenomena populisme global dan penggunaan platform digital dalam membentuk opini publik serta memengaruhi hasil pemilu.
Adapun pada periode paling mutakhir, yakni 2022 hingga 2024, peta overlay menunjukkan adanya pergeseran fokus yang lebih tajam ke isu-isu seperti polarisasi politik, nasionalisme baru (new nationalism), politik media sosial, serta wacana identitas dalam ranah transnasional. Tema-tema ini merefleksikan tantangan baru dalam demokrasi kontemporer, di mana politik identitas semakin dipengaruhi oleh algoritma digital, ekonomi perhatian (attention economy), serta penyebaran disinformasi yang memperkuat segregasi sosial dan memicu konflik simbolik yang berskala luas.
Dengan demikian, overlay map tidak hanya menunjukkan perkembangan kronologis tema, tetapi juga mengilustrasikan pergeseran orientasi akademik dari fokus awal pada agama dan etnisitas ke arah isu-isu yang lebih struktural dan sistemik dalam politik digital dan demokrasi global. Pergeseran ini menandai evolusi wacana politik identitas dari sekadar fenomena sosial ke isu strategis yang menyentuh inti dari stabilitas politik dan kohesi sosial dalam masyarakat kontemporer.
Density Visualization Politik Identitas
Peta densitas (density visualization) memberikan gambaran mengenai konsentrasi dan intensitas tema-tema yang paling sering muncul dalam literatur mengenai politik identitas. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa area dengan kepadatan tertinggi terletak pada istilah-istilah seperti politik identitas, agama, etnis, serta isu-isu yang berkaitan dengan pemilu, pilkada, dan demokrasi elektoral. Ini menegaskan bahwa hingga saat ini, inti kajian politik identitas masih sangat berfokus pada dimensi identitas komunal dan ekspresinya dalam konteks politik elektoral. Dominasi tema-tema ini mencerminkan perhatian yang besar terhadap bagaimana identitas agama dan etnis digunakan sebagai alat mobilisasi politik serta pengaruhnya terhadap dinamika demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.
Di luar inti utama tersebut, terdapat area dengan kepadatan menengah yang mencakup istilah seperti populisme, konflik, dan nasionalisme. Meskipun tidak sepadat inti kajian utama, tema-tema ini mulai mendapatkan perhatian lebih besar dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan munculnya pemimpin populis, menguatnya sentimen nasionalistik, dan meningkatnya potensi konflik horizontal berbasis identitas. Namun demikian, visualisasi densitas juga memperlihatkan adanya area pinggiran yang belum banyak dijelajahi oleh literatur, seperti politik media sosial, politik transnasional, dan polarisasi politik. Tema-tema ini muncul dengan frekuensi yang rendah, tetapi sangat relevan dalam konteks kontemporer, terutama di era digital dan globalisasi, di mana identitas politik tidak hanya terbentuk secara lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh arus informasi lintas batas dan ekosistem media daring.
Dengan demikian, density map menegaskan bahwa kajian politik identitas masih bertumpu pada isu-isu klasik seperti agama, etnis, dan demokrasi, namun juga membuka peluang eksplorasi baru di wilayah yang masih jarang disentuh, seperti dampak politik digital, perubahan konfigurasi identitas dalam konteks transnasional, dan proses polarisasi ideologis dalam masyarakat. Wilayah-wilayah pinggiran ini dapat menjadi frontier penelitian baru yang penting untuk dikembangkan, guna memahami dinamika politik identitas dalam lanskap demokrasi yang semakin kompleks dan terfragmentasi.
Celah PenelitianPolitik Identitas
Analisis terhadap literatur politik identitas dalam sepuluh tahun terakhir mengungkap sejumlah kesenjangan penelitian yang masih terbuka luas untuk dieksplorasi. Secara temporal, kajian yang dominan hingga periode 2020 masih sangat berfokus pada politik identitas berbasis agama dan etnisitas, khususnya dalam konteks konflik sosial dan mobilisasi elektoral di Indonesia. Padahal, dalam lima tahun terakhir telah muncul dinamika baru yang mengubah lanskap politik identitas secara signifikan, termasuk isu-isu seperti politik digital, polarisasi ideologis, pengaruh algoritma media sosial, serta nasionalisme baru dalam era globalisasi. Sayangnya, isu-isu ini masih belum mendapatkan porsi perhatian yang sepadan dalam studi-studi akademik, sehingga membuka peluang untuk memperluas horizon penelitian ke arah yang lebih relevan dengan konteks kontemporer.
Dari sisi konseptual, literatur yang ada cenderung membingkai politik identitas sebagai fenomena konflik, mobilisasi massa, atau instrumen populisme. Namun, pendekatan semacam ini belum banyak mengaitkan politik identitas dengan kerangka yang lebih konstruktif, seperti demokrasi deliberatif, partisipasi warga (civic engagement), dan rekonsiliasi sosial. Selain itu, kajian yang menghubungkan politik identitas dengan dinamika transnasional seperti migrasi, diaspora, globalisasi budaya, atau gerakan identitas lintas batas masih sangat terbatas, padahal koneksi antara identitas lokal dan global semakin kompleks di era digital.
Kesenjangan juga tampak dari aspek metodologis. Studi-studi yang ada masih didominasi oleh pendekatan kualitatif berbasis wacana, studi kasus, atau analisis naratif atas peristiwa-peristiwa besar seperti Pilkada DKI Jakarta 2017. Belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif digital, seperti analisis big data media sosial, sentiment analysis, atau network analysis untuk memetakan pola mobilisasi identitas dan pengaruh algoritmik terhadap pembentukan opini publik. Di sisi lain, pendekatan komparatif lintas negara atau lintas wilayah di Indonesia juga masih jarang dilakukan, meskipun fenomena politik identitas juga merebak di berbagai negara demokrasi lainnya seperti India, Turki, maupun negara-negara Eropa Timur.
Terakhir, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam mengaitkan konteks lokal dengan dinamika global. Studi-studi politik identitas di Indonesia masih sangat terfokus pada Islam politik dan etnisitas lokal, sementara hubungan dengan tren global seperti kebangkitan populisme kanan, politik imigrasi, dan nasionalisme digital belum banyak disentuh. Padahal, mengaitkan fenomena identitas lokal dengan kerangka global dapat memperkuat posisi studi Indonesia dalam literatur internasional, sekaligus membuka jalan bagi refleksi kritis atas dinamika demokrasi dan keberagaman di era global.
Novelty Kebaharuan Politik Identitas
Berdasarkan analisis tren literatur dan pemetaan visualisasi bibliometrik, terdapat sejumlah kebaruan (novelty) yang dapat dikembangkan untuk memperkaya kajian politik identitas, khususnya dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara. Salah satu arah kebaruan yang menonjol adalah pengembangan studi politik identitas dalam konteks era digital. Perubahan ekosistem informasi yang dipengaruhi oleh algoritma media sosial, disinformasi, dan fenomena echo chamber telah mengubah cara identitas politik terbentuk, disebarluaskan, dan dimobilisasi. Oleh karena itu, studi tentang digital populism dan cyber mobilization berbasis identitas menjadi sangat relevan untuk melihat bagaimana media digital memperkuat polarisasi atau sebaliknya, membuka ruang bagi representasi politik yang lebih inklusif.
Di samping itu, kebaruan konseptual juga dapat dikembangkan melalui pendekatan yang tidak hanya memandang politik identitas sebagai medan konflik dan mobilisasi, melainkan juga sebagai ruang potensial untuk rekonsiliasi, partisipasi warga (civic engagement), dan penguatan demokrasi deliberatif. Pendekatan ini membuka peluang untuk melihat dinamika politik identitas secara lebih konstruktif, terutama dalam konteks masyarakat majemuk yang rentan terhadap segregasi sosial dan polarisasi ideologis. Dalam kerangka ini, studi tentang inisiatif lokal, gerakan lintas identitas, dan praktik deliberasi warga dapat menjadi kontribusi penting dalam memperluas pemahaman terhadap politik identitas yang transformatif.
Selain itu, terdapat potensi besar untuk mengembangkan kajian yang menyoroti interseksi identitas, yakni bagaimana dimensi agama, etnis, gender, dan kelas sosial saling berkelindan dalam membentuk posisi politik seseorang atau kelompok. Pendekatan ini menuntut analisis yang lebih interdisipliner, yang menggabungkan perspektif ilmu politik, sosiologi, dan studi gender, serta memungkinkan pemahaman yang lebih kompleks terhadap dinamika identitas di tengah perubahan sosial yang cepat. Interseksi ini juga penting dalam membaca ulang relasi kuasa dan representasi dalam arena politik, baik formal maupun informal.
Dari sisi geografis dan komparatif, kebaruan dapat dikembangkan melalui pendekatan komparatif antara Global South dan Global North. Politik identitas di Indonesia, misalnya, dapat dibandingkan dengan fenomena serupa di negara-negara seperti India (dalam konteks politik Hindu nasionalis), Eropa (terkait politik imigrasi dan populisme kanan), atau Amerika Serikat (melalui wacana nasionalisme digital dan gerakan identitas rasial). Studi semacam ini tidak hanya akan memperkuat kontribusi kajian Indonesia dalam diskursus global, tetapi juga memperkaya analisis dengan perspektif lintas konteks.
Terakhir, arah kebaruan yang menjanjikan adalah kajian tentang isu-isu transnasional dalam politik identitas, seperti peran diaspora, globalisasi budaya, atau gerakan transnasional dalam membentuk identitas politik baru. Fenomena ini mulai terlihat di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di mana ekspresi identitas politik tidak lagi terbatas pada batas-batas nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman migrasi, jaringan global, serta dinamika politik internasional. Dengan demikian, pengembangan arah riset ini berpotensi memberikan kontribusi teoritis dan empiris yang signifikan dalam memahami evolusi politik identitas di era global yang semakin terkoneksi.
file pdf dapat diunduh disini