Pengertian Public Value
Moore (1995, 28) mendefinisikan public value sebagai nilai yang diciptakan pemerintah melalui kebijakan, program, dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Nilai publik tercapai apabila kebijakan pemerintah dapat meningkatkan legitimasi politik, kepuasan masyarakat, dan efektivitas manajerial.
Menurut Benington (2009, 234), public value adalah hasil interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menciptakan nilai bersama. Nilai publik tidak hanya diproduksi oleh pemerintah, tetapi juga oleh jejaring kolaboratif lintas aktor yang berkontribusi pada kepentingan kolektif.
Bryson dkk (2014, 447) mendefinisikan public value sebagai kerangka kerja normatif dan analitis yang digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah dan organisasi publik menghasilkan nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Penekanan diberikan pada dimensi legitimasi, akuntabilitas, dan kinerja layanan publik.
(Talbot 2009, 7) menyatakan bahwa public value merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik berdasarkan kontribusinya terhadap kepentingan masyarakat luas. Nilai publik mencakup aspek kepuasan warga, keadilan sosial, dan keberlanjutan pelayanan.
Menurut (O’Flynn 2007, 353), public value adalah paradigma tata kelola publik yang menekankan kolaborasi, partisipasi, dan inovasi untuk mencapai hasil yang bernilai bagi masyarakat. Konsep ini menjadi alternatif dari paradigma New Public Management yang cenderung berorientasi pasar.
Public value dipahami sebagai kerangka strategis yang dikembangkan oleh Mark Moore (1995) melalui segitiga strategis yang mencakup tiga aspek utama: legitimasi dan dukungan, kapasitas operasional, serta nilai substansial. Konsep ini menekankan bahwa program publik dinilai bermanfaat apabila memperoleh legitimasi dari lingkungan politik, memiliki kapasitas operasional memadai, serta menghasilkan nilai substansial bagi masyarakat.
Public value dimaknai sebagai nilai yang diciptakan sektor publik melalui layanan, manfaat, dan kepercayaan. (Mark Harrison Moore 1995) menegaskan bahwa public value merupakan hasil pemikiran strategis para pembuat kebijakan dan manajer publik dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan. Indikatornya dapat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat, akses informasi, efisiensi biaya layanan, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah
Public value dipahami sebagai nilai dan manfaat yang dihasilkan oleh program pemerintah yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam penelitian tentang Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda di Surabaya, nilai publik muncul ketika program mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan, serta memberikan manfaat ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, public value tidak hanya menjadi ukuran kinerja formal, tetapi juga tercermin dari manfaat nyata yang diterima publik (Hadis 2020, 5–7)
Public value didefinisikan sebagai komposisi nilai yang terus berubah dalam proses transformasi sistem publik, termasuk kepercayaan, inklusivitas, transparansi, legitimasi, efektivitas, privasi, dan akuntabilitas. Laporan ini menekankan bahwa public value terbentuk dalam konteks perubahan sistem yang kompleks, di mana pemerintah tidak lagi mampu mendefinisikan perubahan dari atas, melainkan harus mengembangkan proses partisipatif dengan warga. Dengan demikian, menjadi kerangka normatif yang menuntun perubahan sistem, pengambilan keputusan, serta legitimasi demokratis dalam tata kelola publik (OECD 2019, 11–13, 27–30)
Nilai publik pada dasarnya adalah bagaimana masyarakat menilai sebuah organisasi, pelayanan, program dan lain sebagainya. Penciptaan nilai publik dibangun dari suatu strategi organisasional yakni Trilogi Strategi (a strategic triangle) yang dipopulerkan oleh Mark Moore. Spano berpendapat bahwa nilai publik dapat tercapai bilamana layanan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik memenuhi kebutuhan penduduk, sehingga semakin tinggi kepuasan masyarakat, semakin besar nilai publik yang diciptakan (Spano 2009).
Berbicara mengenai nilai publik itu sendiri, nilai publik dapat diartikan sebagai sebuah pemikiran dan tindakan strategis oleh para pembuat kebijakan publik dan manajer, dalam menghadapi kompleksitas dan penghematan atau sebuah sarana populer untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Moore, 1995).
Indikator Public Value
Konsep public value memiliki dimensi yang beragam sesuai dengan konteks kebijakan publik yang dikaji. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur public value berdasarkan literatur dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pengukuran public value didapatkan dari usulan delapan indikator kesuksesan penerapan public value oleh (Kearns 2004). Kedelapan indikator tersebut adalah :
- Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan.
- Meningkatnya level kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
- Meningkatnya informasi dan pilihan yang tersedia bagi masyarakat.
- Menciptakan dan lebih fokus pada pelayanan yang dipercaya oleh masyarakat.
- Meningkatnya fokus pelayanan yang baru dan inovatif sesuai dengan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
- Berkurangnya biaya yang dibutuhkan dalam penyediaan layanan.
- Adanya perbaikan dalam penyampaian hasil (layanan kepada masyarakat).
- Berkontribusi untuk memperbaiki level kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah
Menurut O’Flynn (2009) dalam (MARGIYANI 2021, 20–22) nilai publik memiliki simbol yang dikenal dengan segitiga strategis yang berisi dari tiga aspek yaitu:
- Legitimasi dan Dukungan (Legitimacy and Support) Legitimasi dan dukungan ialah suatu otoritas kepentingan politik dan lainnya yang diberikan dari berbagai dukungan secara sah dan politis, dukungan dan sumberdaya dari lingkungan dengan pengakuan atas otoritas yang diberikan. Legitimasi ialah sahnya suatu keputusan yang dilandasi oleh sebuah suatu landasan hukum, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, maupun hukum tertulis lainnya. Sedangkan dukungan dapat berupa adanya dukungan masyarakat kepada kewenangan yang ada.
- Kemampuan Operasional (Operational Capabilities) Kemampuan operasional ialah tersedianya kemampuan organisasi untuk melaksanakan program. Kemampuan operasional terdiri dari kemampuan mengelola sumber daya 21 manusia, teknologi/infrastruktur dan finansial yang dimiliki untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Secara sederhana kemampuan operasional ialah adanya lembaga yang mampu mengelola program tersebut sehingga dapat menghasilkan nilai publik.
- Nilai Substansial (substantively valuable) Nilai Substansial dalam segitiga strategis ditujukan untuk menciptakan suatu yang secara substansial berharga. Peran administrasi publik termasuk dalam hal pencipta potensi nilai publik selain menjadi penyedia layanan. Benington (2011) menjelaskan bahwa nilai publik memiliki makna melebihi koordinat pasar dan mempertimbangkan faktor politik dan sosial, sebagai berikut:
- Nilai Ekonomi adalah nilai yang menghasilkan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan. Nilai ekonomi dapat diketahui dari manfaat atau keuntungan ekonomi yang diberikan dan diterima oleh sasaran dari dilaksanakannya program ini.
- Nilai Sosial dan Budaya yaitu nilai tambah program memiliki berkontribusi dalam modal sosial, persatuan sosial, hubungan sosial, kesejahteraan individu ataupun kelompok. Nilai sosial dan budaya dapat diketahui dari 22 manfaat sosial dan budaya bagi sasaran dengan adanya program ini.
- Nilai Politik yaitu nilai tambah untuk merangsang dan mendukung demokrasi melalui keterlibatan aktif dan komitmen masyarakat. Nilai politik dapat diketahui dari keterlibatan masyarakat dalam program ini.
- Nilai Pendidikan yaitu nilai tambah dalam peluang pendidikan formal maupun informal, yang terdiri dari tambahan pengetahuan, kemampuan, dan kapasitas. Nilai pendidikan dapat diketahui dari manfaat program ini dalam meningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat.
- Nilai Ekologi yaitu nilai tambah dalam program pemerintah turut mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi polusi, sampah dan pemanasan global. Nilai ekologi dapat diketahui dari pengaruh program ini terhadap lingkungan sekitar masyarakat.
Segitiga Strategis Moore (1995) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- menciptakan nilai publik Dalam menciptakan nilai publik, hal ini merupakan alat manajemen bagaimana manajer merencanakan aktivitas maupun kegiatan yang dapat bernilai, disahkan, dan dapat 24 dilaksanakan. Intinya ialah manajer publik harus mengetahui yang mana program yang harus dilaksanakan atau yang tidak perlu untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai publik. Aspek ini berkaitan erat dengan tujuan, maksud, misi dan target dari suatu program.
- Legitimasi dan dukungan lingkungan Legitimasi dan dukungan lingkungan diartikan bahwa suatu program mendapatkan pengesahan, baik dari dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program maupun dari para pengambil keputusan.
- Kapasitas Operasional Dalam aspek kapasitas operasional, organisasi pelaksana harus dipastikan memiliki kapasitas operasional yang cukup untuk melaksanakan serta mengelola program yang telah disahkan. Kapasitas operasional berkaitan erat dengan pegawai, kompetensi pegawai, teknologi, dan infrastruktur (MARGIYANI 2021, 23–24).
Fenomena
Peluncuran aplikasi WargaKu oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2021 merupakan inovasi digital yang dirancang untuk menampung keluhan, kritik, maupun aspirasi masyarakat secara langsung. Aplikasi ini terintegrasi dengan perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan laporan yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam akan otomatis masuk ke perangkat Wali Kota (Admin surabay.go.id). Inovasi ini memperlihatkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah melalui partisipasi publik.
Pada tahun 2025, Wali Kota Surabaya menginstruksikan agar sistem pengaduan masyarakat yang diterima DPRD diintegrasikan dengan aplikasi WargaKu. Langkah ini bertujuan memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemkot Surabaya dalam merespons aspirasi warga secara efektif (Admin Surabaya.go.id, 2025). Hal ini mencerminkan upaya penciptaan public value melalui koordinasi kelembagaan yang mendorong efisiensi tata kelola dan responsivitas.
Sepanjang tahun 2022, aplikasi WargaKu menerima sebanyak 10.504 laporan masyarakat. Mayoritas aduan berhasil ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian (Admin Surabaya.go.id, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa aplikasi WargaKu tidak hanya diterima masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai saluran utama interaksi warga dengan pemerintah kota.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan kebijakan e-budgeting dan e-voting di sekitar 5.000 desa untuk memperkuat transparansi keuangan sekaligus memperlancar proses demokrasi lokal. Melalui digitalisasi pengelolaan anggaran desa dan pemilihan kepala desa, pemerintah daerah berupaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat legitimasi demokratis di tingkat akar rumput (ANTARA, 2025: 3). Kebijakan ini menjadi contoh implementasi public value governance melalui transformasi digital.
Bank Indonesia memperkenalkan chatbot bernama LISA (Layanan Informasi Bank Indonesia) pada tahun 2020. Chatbot ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui WhatsApp, Line, dan Facebook Messenger. Inovasi ini bertujuan mendekatkan institusi publik dengan warga, memperluas akses informasi resmi, dan meningkatkan kepuasan publik (Buchori, 2020). Dengan demikian, teknologi digital berperan sebagai instrumen penciptaan nilai publik berbasis transparansi dan pelayanan.
Tinjauan Teori
Konsep public value diperkenalkan dan dipopulerkan dalam literatur administrasi publik oleh Mark H. Moore sebagai alternatif orientasi evaluasi organisasi publik yang melampaui ukuran-ukuran teknokratis semata. Moore menegaskan bahwa tujuan utama manajer publik adalah menciptakan nilai publik (creating public value) dari aset-aset yang dipercayakan oleh masyarakat, sehingga kinerja pemerintahan harus dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan publik menghasilkan manfaat kolektif yang diakui oleh publik. Pemaparan konseptual dan kasus-kasus ilustratif ini dipaparkan secara komprehensif dalam buku Moore (1995).
Salah satu kontribusi teoretis paling berpengaruh dari Moore adalah strategic triangle suatu kerangka diagnosis strategis yang menghubungkan tiga unsur:
- public value yang hendak diciptakan (apa yang bernilai bagi publik),
- legitimasi dan dukungan politik yang diperlukan untuk melakukan tindakan (legitimacy & political support)
- kapasitas operasional organisasi untuk melaksanakan tindakan tersebut (operational capacity). Kerangka ini memandu manajer publik untuk menilai apakah suatu peluang strategis layak dikejar: apakah tindakan tersebut menciptakan nilai publik, apakah ada legitimasi/dukungan yang memadai, dan apakah organisasi memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Kerangka ini menjadi referensi dasar untuk banyak studi teori dan praktik manajemen publik berikutnya.
Perluasan konseptual selanjutnya menunjukkan bahwa public value tidak hanya merupakan agregat output/hasil administratif, tetapi juga mengandung dimensi perseptual/subjektif: nilai publik “terbentuk di dalam“ pengalaman warga melalui interaksi sosial, kebutuhan psikologis, dan persepsi legitimasi. Meynhardt (2009) mengembangkan kerangka non-normatif yang menyoroti proses psikologis dan kebutuhan manusia sebagai sumber pembentukan nilai publik, sehingga menuntut metode pengukuran yang memasukkan persepsi dan pengalaman warga sebagai bagian integral dari akuntansi nilai publik. Pendekatan ini mengingatkan peneliti bahwa aspek subjektif (kepuasan, legitimasi emosional, persepsi keadilan) sering menentukan apakah suatu output publik benar-benar bernilai bagi masyarakat.
Literatur selanjutnya menggeser fokus dari manajemen internal organisasi publik ke arena tata kelola yang lebih luas Public Value Governance yang menekankan peran kolektif aktor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam penciptaan nilai publik. Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2014) berargumen bahwa dalam dunia yang bersifat jaringan (networked), penciptaan nilai publik membutuhkan kolaborasi multi-aktor, perlindungan nilai-nilai demokratis, serta mekanisme untuk mengidentifikasi dan memetakan nilai-nilai publik yang saling bertentangan. Paradigma ini menempatkan legitimasi demokratis dan proses prosedural sebagai elemen kunci dalam evaluasi public value.
Upaya operasionalisasi public value mendapat perhatian empiris melalui pengembangan kerangka penilaian. Page, Stone, Bryson, dan Crosby (2015) mengusulkan model pengukuran untuk kolaborasi lintas-sektor berdasarkan tiga dimensi utama:
- democratic accountability (siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akuntabilitas dipertanggungjawabkan),
- procedural legitimacy (kualitas prosedur yang menghasilkan keputusan)
- substantive outcomes (hasil/ dampak sebenarnya bagi publik). Kerangka ini menyoroti tantangan pengukuran seperti atribusi nilai dalam kolaborasi, trade–off antar-dimensi, dan kebutuhan pelacakan jangka panjang.
Untuk menjembatani klaim normatif dan kebutuhan pengukuran, Moore (2014) mengusulkan dasar-dasar filosofis bagi praktik public value accounting. Ia membahas pertanyaan mendasar: siapa yang berwenang menilai nilai publik (kolektif demokratis), aset kolektif apa yang menjadi objek penilaian (uang publik, wewenang negara, kepercayaan sosial), serta prinsip etis yang harus dipertimbangkan (utilitarian vs deontologis). Moore menekankan bahwa praktik akuntansi ini harus transparan secara normatif dan metodologis agar dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. Pada praktiknya, desain indikator yang menggabungkan dimensi objektif (kinerja) dan subjektif (persepsi) serta legitimasi prosedural masih merupakan tantangan besar.
Konsep public value muncul sebagai respon terhadap keterbatasan paradigma New Public Management (NPM) yang cenderung menekankan efisiensi, kompetisi, dan logika pasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, public value menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan menekankan legitimasi demokratis, partisipasi warga, dan penciptaan nilai bersama (co-created value) bagi masyarakat luas (O’Flynn, 2007: 354).
Moore (1995: 28) menekankan bahwa public value merupakan nilai yang diciptakan pemerintah ketika program, kebijakan, dan layanan publik mampu memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penciptaan nilai publik membutuhkan keseimbangan antara legitimasi politik, dukungan masyarakat, serta kapasitas manajerial pemerintah.
Sejalan dengan hal tersebut, Benington (2009: 234) memperluas pengertian public value dengan menekankan bahwa nilai publik tidak hanya dihasilkan oleh pemerintah, tetapi juga melalui jejaring kolaboratif yang melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta. Hal ini menegaskan bahwa penciptaan nilai publik adalah hasil interaksi lintas aktor, bukan monopoli negara.
Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2014: 447) menguraikan public value governance sebagai paradigma baru dalam tata kelola publik yang menekankan kolaborasi, akuntabilitas, serta kemampuan organisasi publik untuk memberikan layanan yang bernilai sesuai harapan masyarakat. Dengan kata lain, nilai publik tercipta ketika terdapat legitimasi, transparansi, dan hasil pelayanan yang diakui oleh warga negara.
Talbot (2009: 7) menambahkan bahwa public value juga dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja sektor publik. Fokusnya tidak hanya pada efisiensi administratif, tetapi juga pada kepuasan warga, keadilan sosial, dan keberlanjutan kebijakan. Perspektif ini memungkinkan pengukuran kinerja pemerintah berdasarkan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penelitian Terdahulu
Kajian literatur mengenai public value menunjukkan adanya perkembangan teori dan aplikasi yang signifikan. Moore (1995) menekankan pada aspek konseptual dan kerangka strategis melalui strategic triangle yang menjadi dasar dalam manajemen sektor publik. Namun, penelitian ini masih terbatas pada level normatif dan belum menguji implementasi secara luas di konteks pemerintahan lokal maupun nasional.
Meynhardt (2009) memberikan perspektif psikologi sosial dengan menekankan peran persepsi individu dalam membentuk nilai publik. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menjelaskan mekanisme implementasi nilai publik dalam kebijakan maupun layanan publik secara konkret.
Sementara itu, Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2014) memperkenalkan paradigma Public Value Governance yang menawarkan pendekatan alternatif dari administrasi publik tradisional dan New Public Management. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum secara rinci memberikan indikator operasional untuk mengukur keberhasilan penciptaan nilai publik.
Page, Stone, Bryson, dan Crosby (2015) berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan kerangka tiga dimensi (akuntabilitas demokratis, legitimasi prosedural, dan hasil substantif) melalui studi kasus kolaborasi lintas sektor. Walaupun demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus geografis yang sempit dan konteks kasus tertentu, sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas.
Terakhir, Moore (2014) menekankan pentingnya dasar filosofis dalam public value accounting, namun kerangka tersebut belum secara operasional diuji di lapangan, terutama dalam konteks pemerintahan daerah yang menghadapi dinamika politik, sosial, dan birokrasi yang kompleks.
Berdasarkan celah penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kajian public value yang lebih aplikatif, terutama pada konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana nilai publik dapat diwujudkan melalui praktik tata kelola, kepemimpinan digital, maupun inovasi pelayanan publik yang berbasis partisipasi masyarakat.
Perkembangan literatur mengenai public value menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam administrasi publik dari sekadar orientasi kinerja berbasis efisiensi menuju orientasi yang lebih luas pada nilai sosial yang dihasilkan bagi masyarakat. Moore (1995) meletakkan dasar konseptual dengan memperkenalkan strategic triangle yang menekankan hubungan antara nilai publik, legitimasi politik, dan kapasitas operasional sebagai kerangka manajemen sektor publik. Perspektif ini kemudian diperluas oleh Meynhardt (2009) yang menekankan bahwa public value muncul dari pengalaman subjektif individu dan dipengaruhi oleh interaksi sosial serta legitimasi emosional yang dirasakan.
Sejalan dengan itu, Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2014) mengajukan paradigma Public Value Governance yang berupaya melampaui pendekatan New Public Management dengan menekankan kolaborasi multi-aktor, demokrasi prosedural, serta legitimasi sebagai pilar utama tata kelola publik. Upaya operasionalisasi lebih lanjut dilakukan oleh Page, Stone, Bryson, dan Crosby (2015) yang mengembangkan kerangka penilaian public value melalui tiga dimensi utama: akuntabilitas demokratis, legitimasi prosedural, dan hasil substantif. Di sisi lain, Moore (2014) menekankan perlunya landasan filosofis bagi public value accounting untuk menjawab pertanyaan mendasar terkait siapa yang berwenang menilai, aset kolektif apa yang dinilai, serta prinsip normatif apa yang digunakan.
Dengan demikian, state of the art dari kajian public value menunjukkan bahwa meskipun kerangka teoritis dan konseptual telah berkembang cukup matang, masih terdapat keterbatasan dalam aspek pengukuran operasional, validasi empiris lintas konteks, serta penerapannya dalam pemerintahan daerah, khususnya di negara berkembang.
Daftar Pustaka (APSA) :
Admin Surabaya.go.id. 2021. “Ingin Dengarkan Kritik Dan Saran Warga, Pemkot Surabaya Rilis Aplikasi WargaKu.” surabaya.go.id. https://surabaya.go.id/id/berita/59474/ingin-dengarkan-kritik-dan-saran-warga-pemkot-surabaya-rilis-aplikasi-wargaku.
Admin Surabaya.go.id. 2022. “Selama 2022, Aplikasi WargaKu Surabaya Terima 10.504 Pengaduan.” surabaya.go.id. https://surabaya.go.id/id/berita/11038/selama-2022-aplikasi-wargaku-surabaya-terima-10504-pengaduan.
Admin Surabaya.go.id. 2025. “Pemkot Surabaya Integrasikan Aduan DPRD Dengan Aplikasi WargaKu.” surabaya.go.id. https://surabaya.go.id/id/berita/23525/pemkot-surabaya-integrasikan-aduan-dprd-dengan-aplikasi-warga-ku.
Benington, John. 2009. Public Value: Theory and Practice. London: Palgrave MacMillan.
Bryson, John M., Barbara C. Crosby, and Laura Bloomberg. 2014. “Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management.” Public Administration Review 74(4): 445–56. doi:10.1111/puar.12238.
Buchori, Ahmad. 2020. “Tingkatkan Layanan Publik, BI Luncurkan Chatbot LISA.” antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/1829092/tingkatkan-layanan-publik-bi-luncurkan-chatbot-lisa.
Hadis, Ageta Sofia. 2020. “Nilai Publik (Public Value) Dari Program Pahlawan Ekonomi Dan Pejuang Muda Di Kota Surabaya.” http://repository.unair.ac.id/id/eprint/101373.
Kearns, Ian. 2004. Public Value and E-Government. London: Institute for Public Policy Research London.
Meynhardt, Timo. 2009. “Public Value Inside: What Is Public Value Creation?” International Journal of Public Administration 32(3–4): 192–219. doi:10.1080/01900690902732632.
Moore, Mark H. 2012. Recognizing Public Value. Harvard University Press.
Moore, Mark H. 2014. “Public Value Accounting: Establishing the Philosophical Basis.” Public Administration Review 74(4): 465–77. doi:10.1111/puar.12198.
Moore, Mark Harrison. 1995. Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard: Harvard University Press.
OECD. 2019. Public Value in Public Service Transformation. New York: OECD. doi:10.1787/47c17892-en.
O’Flynn, Janine. 2007. “From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications.” Australian Journal of Public Administration 66(3): 353–66. doi:10.1111/j.1467-8500.2007.00545.x.
Prayoga. 2025. “Jabar Resmi Menerapkan E-Budgeting Dan e-Voting Di Desa.” antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/4876565/jabar-resmi-menerapkan-e-budgeting-dan-e-voting-di-desa.
Spano, Alessandro. 2009. “Public Value Creation and Management Control Systems.” International Journal of Public Administration 32(3–4): 328–48. doi:10.1080/01900690902732848.
Talbot, Colin. 2009. “Public Value—The Next ‘Big Thing’ in Public Management?” International Journal of Public Administration 32(3–4): 167–70. doi:10.1080/01900690902772059.
file pdf download disini
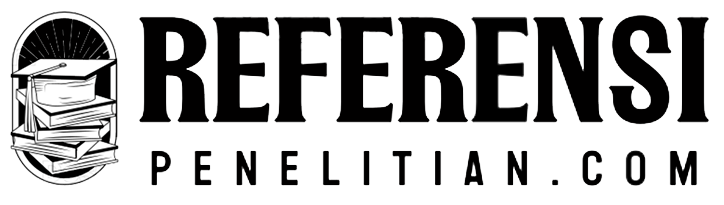

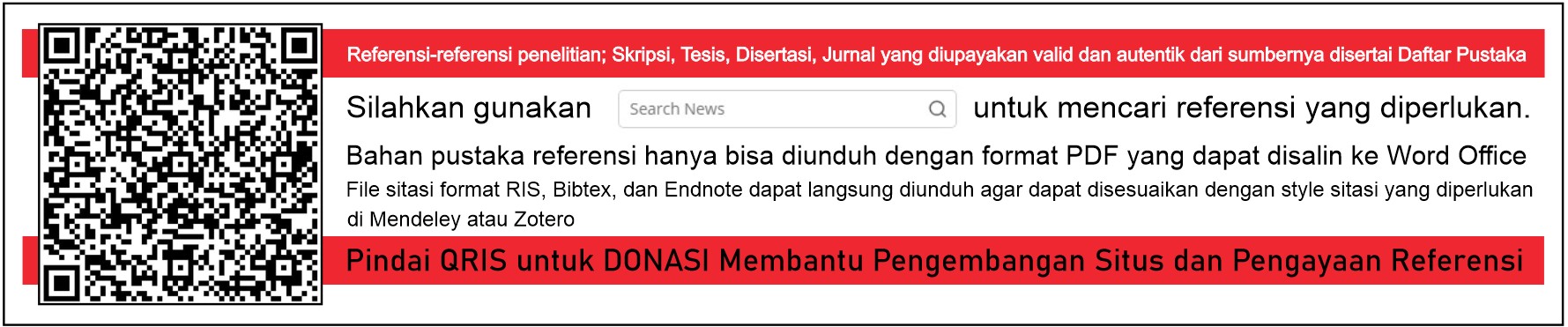
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.