Latar Belakang
Pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi kritis, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Salah satu upaya strategis untuk mencapainya adalah melalui pembelajaran matematika di sekolah dasar. Namun, kenyataannya matematika kerap dipersepsikan sulit sehingga menurunkan minat belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teori belajar yang mampu meningkatkan pemahaman sekaligus motivasi siswa. Teori belajar kognitif dipandang relevan karena menekankan keterlibatan aktif siswa dalam mengolah informasi dan mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Dengan demikian, penerapan teori kognitif dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses belajar siswa (Ritonga & Wandini, 2023, hlm. 29899)
Kognitif secara etimologis berarti berpikir (cogitare) dan dalam kajian psikologi pendidikan mencakup aktivitas mental seperti memahami, mengingat, menalar, serta memecahkan masalah (Nasution, 2011, hlm. 17; Suharti, 2011, hlm. 28). Teori kognitif muncul sebagai kritik terhadap behaviorisme yang memandang belajar sebatas hubungan stimulus–respon (Soemanto, 2003, hlm. 45). Dalam praktik pendidikan dasar, teori ini sangat penting karena menekankan keterlibatan aktif siswa dalam mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman belajar dan interaksi sosial. Dengan demikian, penerapan teori belajar kognitif di sekolah dasar diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna (Pahru dkk., 2023, hlm. 1071)
Teori pembelajaran berfungsi sebagai dasar konseptual bagi guru dalam merancang strategi mengajar yang efektif. Di antara berbagai teori, kognitif dan konstruktivisme menempati posisi penting karena menekankan proses berpikir, pemecahan masalah, serta keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan. Kedua teori ini melahirkan pendekatan seperti discovery learning dan meaningful learning yang relevan dengan tuntutan pendidikan modern (Arifin, 2021, hlm. 22; Budyastuti & Fauziati, 2021, hlm. 41). Dengan memahami dan menerapkan teori kognitif dan konstruktivisme, guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan abad 21 (Habsy dkk., 2024, hlm. 309–310)
Teori pembelajaran berfungsi menjelaskan mekanisme terjadinya proses belajar sehingga dapat dijadikan acuan dalam praktik pendidikan. Teori kognitivisme secara khusus lebih menekankan pada bagaimana peserta didik memproses informasi dibandingkan sekadar menilai hasil belajarnya. Tokoh-tokoh utama seperti Piaget, Bruner, Ausubel, dan Gagne menegaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses mental yang aktif dan sistematis. Menurut Bruner, teori pembelajaran juga berperan dalam mendukung profesionalitas guru, khususnya dalam merancang kurikulum yang kontekstual dan sesuai kebutuhan peserta didik (Nurhadi, 2020, hlm. 77–79)
Belajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan, karena melalui proses belajar terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa (Pane & Dasopang, 2017, hlm. 2). Teori kognitif, sebagaimana dikembangkan oleh Piaget, Bruner, dan Ausubel, menekankan bahwa belajar adalah proses mental aktif yang menghubungkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki individu (Sutarto, 2017, hlm. 3). Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, teori kognitif relevan karena dapat membantu siswa memahami konsep secara mendalam, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, serta mengembangkan kemampuan reflektif. Hal ini menjadikan teori kognitif sebagai salah satu landasan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah (Nurdiyanto dkk., 2023, hlm. 8810–8811)
Salah satu tantangan utama dalam pendidikan dasar adalah menciptakan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga mendorong perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Selama ini, pendekatan behavioristik masih dominan digunakan, yang cenderung menekankan hafalan dan pengulangan. Padahal, pembelajaran yang hanya berorientasi pada hasil kurang mampu menumbuhkan pemahaman yang mendalam. Teori belajar kognitif hadir sebagai solusi karena lebih menekankan proses berpikir siswa, keterlibatan mental, dan interaksi sosial sebagai faktor penting dalam mengonstruksi pengetahuan (Pahru dkk., 2023, hlm. 1072).
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital menuntut pendidikan untuk melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif. Teori pembelajaran, khususnya kognitif dan konstruktivisme, menawarkan kerangka konseptual bagi guru dalam merancang pembelajaran yang menekankan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pembelajaran bermakna. Implementasi kedua teori ini dapat mendorong lahirnya inovasi dalam pembelajaran, misalnya melalui pendekatan discovery learning dan meaningful learning (Habsy dkk., 2024, hlm. 310). Latar belakang ini menunjukkan pentingnya pemahaman teori kognitif dan konstruktivisme untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan abad 21.
Dalam praktik pendidikan, masih banyak guru yang menekankan aspek hasil belajar tanpa memahami proses belajar siswa. Akibatnya, pembelajaran cenderung berorientasi pada pencapaian angka semata, bukan pada pemahaman mendalam. Teori kognitivisme hadir untuk menggeser paradigma tersebut dengan menekankan proses mental aktif dalam membangun pengetahuan. Tokoh-tokoh seperti (Ausubel, Novak, dan Hanesian 1978; Bruner 1974; Gagné 1985; Piaget 2013) memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan bagaimana peserta didik mengkonstruksi pengetahuan melalui asimilasi, akomodasi, dan pemrosesan informasi. Dengan memahami teori ini, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan kondisi sosial budaya siswa (Nurhadi, 2020, hlm. 78–79).
Tinjauan Pustaka
Penelitian Ritonga & Wandini (2023, hlm. 29899) mengungkapkan bahwa lebih dari 65% siswa SD Negeri No. 060909 mengalami kesulitan memahami konsep dasar matematika, dengan hanya 40% siswa yang berhasil mencapai nilai KKM. Temuan ini menegaskan perlunya penerapan teori kognitif yang berfokus pada pembelajaran bermakna.
Hal serupa ditegaskan oleh Pahru dkk. (2023, hlm. 1072), yang melaporkan bahwa 60% guru SD masih menggunakan pendekatan behavioristik, sementara 75% siswa lebih mudah memahami materi melalui aktivitas berbasis kognitif. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan antara praktik pembelajaran yang digunakan guru dan kebutuhan belajar siswa.
Dalam skala lebih luas, Habsy dkk. (2024, hlm. 310) menemukan bahwa 80% guru menyatakan penerapan teori kognitif dan konstruktivisme mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa di kelas. Pendekatan discovery learning bahkan terbukti meningkatkan hasil belajar rata-rata hingga 27%, memperkuat argumentasi bahwa teori ini relevan dengan tuntutan pendidikan abad 21.
Nurhadi (2020, hlm. 78) juga menyoroti bahwa 70% guru masih berorientasi pada hasil belajar semata. Padahal, kajian Gagne menunjukkan bahwa pendekatan kognitif dapat meningkatkan retensi materi hingga 40%, yang berarti lebih efektif dalam membantu siswa memahami dan mengingat informasi.
Dalam ranah Pendidikan Agama Islam, Nurdiyanto dkk. (2023, hlm. 8811) menemukan bahwa 75% guru PAI masih mengandalkan metode hafalan. Namun, penelitian mereka menunjukkan penerapan teori kognitif mampu meningkatkan pemahaman konsep keagamaan siswa sebesar 25–35%, memperlihatkan urgensi integrasi teori ini dalam pembelajaran berbasis nilai.
Tinjauan Teori
Menurut Piaget (1972, hlm. 45), anak belajar melalui proses asimilasi dan akomodasi yang mengintegrasikan pengalaman baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Bruner (1966, hlm. 21) menegaskan pentingnya pembelajaran melalui representasi enaktif, ikonik, dan simbolik. Sedangkan Ausubel (1968, hlm. 128) menekankan konsep meaningful learning, yaitu pembelajaran yang terjadi ketika informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Dalam konteks pembelajaran matematika, teori-teori ini mendukung penciptaan pembelajaran bermakna (Ritonga & Wandini, 2023, hlm. 29899)
Penelitian ini menggunakan teori kognitif sebagai kerangka berpikir. Piaget (1972, hlm. 50) menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui tahapan sensori-motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Bruner (1960, hlm. 22) menekankan discovery learning, yakni belajar dengan menemukan konsep sendiri. Ausubel (1968, hlm. 128) menjelaskan bahwa pembelajaran bermakna terjadi bila materi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Teori-teori ini dipandang lebih sesuai dibandingkan behaviorisme, karena memberi peran aktif siswa dalam mengonstruksi pengetahuan (Pahru dkk., 2023, hlm. 1072)
Landasan teori penelitian ini menggabungkan teori kognitif dan konstruktivisme. Teori kognitif menekankan peran proses mental dalam belajar, di mana siswa aktif mengolah informasi Neisser (1976, hlm. 34) dalam (Lichtenstein 1977). Sementara konstruktivisme, sebagaimana dikembangkan oleh Vygotsky (1978, hlm. 86), memandang belajar sebagai hasil interaksi sosial dengan zona perkembangan proksimal (zone of proximal development). Kedua teori ini menegaskan pentingnya pembelajaran bermakna yang mendorong siswa berpikir kritis, reflektif, dan mampu menemukan pengetahuan melalui pengalaman belajar. Hal ini mendukung implementasi model discovery learning dan problem-based learning (Habsy dkk., 2024, hlm. 310)
Piaget (1972, hlm. 46) menjelaskan konsep asimilasi dan akomodasi sebagai mekanisme utama perkembangan kognitif. Bruner (1966, hlm. 23) menekankan spiral curriculum dan discovery learning. Ausubel (1968, hlm. 128) mengajukan teori belajar bermakna yang menekankan peran advance organizer. Gagne (1985, hlm. 44) menyusun hierarki belajar yang menempatkan keterampilan intelektual dan strategi kognitif sebagai dasar penguasaan pengetahuan. Landasan ini menegaskan bahwa proses belajar adalah aktivitas mental yang aktif dan terstruktur (Nurhadi, 2020, hlm. 77–79)
Piaget (1972, hlm. 50) menjelaskan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika siswa mengonstruksi pengetahuan melalui tahapan perkembangan kognitif. Bruner (1960, hlm. 22) menekankan pentingnya scaffolding dalam membantu siswa belajar. Ausubel (1968, hlm. 128) menjelaskan bahwa pemahaman konsep akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman siswa. Vygotsky (1978, hlm. 86) menambahkan dimensi sosial melalui zone of proximal development. Landasan ini menjadikan teori kognitif relevan untuk meningkatkan mutu pembelajaran agama (Nurdiyanto dkk., 2023, hlm. 8811)
Piaget (1972, hlm. 45) menegaskan bahwa perkembangan intelektual berlangsung melalui proses asimilasi dan akomodasi yang memungkinkan siswa mengintegrasikan pengalaman baru ke dalam struktur kognitif yang sudah dimiliki. Bruner (1966, hlm. 21) menambahkan pentingnya tahapan representasi enaktif, ikonik, dan simbolik dalam mendukung pemahaman konsep. Sementara itu, Ausubel (1968, hlm. 128) menekankan bahwa pembelajaran bermakna terjadi ketika materi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, stimulus berupa materi matematika diproses melalui aktivitas mental siswa sehingga menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam (Ritonga & Wandini, 2023, hlm. 29899)
Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget (1972, hlm. 50), yang menekankan pentingnya pengalaman konkret dalam membangun kemampuan berpikir abstrak. Bruner (1960, hlm. 22) melalui konsep discovery learning menegaskan bahwa siswa perlu dilibatkan dalam penemuan konsep agar pembelajaran menjadi bermakna. Ausubel (1968, hlm. 128) menggarisbawahi peran advance organizer untuk menghubungkan informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Oleh karena itu, kerangka ini memandang bahwa stimulus yang diberikan guru akan diolah secara aktif oleh siswa melalui proses berpikir kritis, yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran (Pahru dkk., 2023, hlm. 1072)
Neisser (1976, hlm. 34) dalam (Lichtenstein 1977) menekankan bahwa proses kognitif melibatkan atensi, persepsi, memori, dan penalaran dalam mengolah stimulus pembelajaran. Sementara itu, konstruktivisme menurut Vygotsky (1978, hlm. 86) menegaskan pentingnya interaksi sosial dalam zone of proximal development untuk membangun pengetahuan secara kolaboratif. Kombinasi kedua perspektif ini mengarah pada penerapan strategi pembelajaran berbasis discovery learning dan problem-based learning yang menekankan keaktifan siswa, sehingga berimplikasi pada penguatan keterampilan berpikir kritis dan reflektif (Habsy dkk., 2024, hlm. 310)
Piaget (1972, hlm. 46) menekankan mekanisme asimilasi dan akomodasi dalam perkembangan kognitif. Bruner (1966, hlm. 23) menekankan pentingnya spiral curriculum dan discovery learning. Ausubel (1968, hlm. 128) memperkenalkan advance organizer sebagai penghubung antara informasi baru dan pengetahuan lama. Sementara itu, Gagne (1985, hlm. 44) menguraikan hierarki belajar yang mengarahkan siswa dari keterampilan sederhana menuju kemampuan kompleks. Dengan demikian, kerangka ini menegaskan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada proses kognitif akan menghasilkan retensi dan pemahaman yang lebih mendalam (Nurhadi, 2020, hlm. 77–79)
Piaget (1972, hlm. 50) menekankan pentingnya tahapan perkembangan kognitif dalam memahami materi abstrak. Bruner (1960, hlm. 22) menekankan konsep scaffolding yang diberikan guru untuk mendukung proses internalisasi pengetahuan. Ausubel (1968, hlm. 128) menjelaskan bahwa pembelajaran agama akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Vygotsky (1978, hlm. 86) melalui konsep zone of proximal development menambahkan dimensi sosial dalam proses belajar. Oleh karena itu, teori kognitif dipandang mampu meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus membentuk karakter religius siswa (Nurdiyanto dkk., 2023, hlm. 8811)
Daftar Pustaka (APSA) :
Arifin, Shokhibul. 2021. “Teori Kognitif Dalam Perencanaan Pembelajaran.” TADARUS 10(2). doi:10.30651/td.v10i2.14826.
Ausubel, David Paul, Joseph Donald Novak, and Helen Hanesian. 1978. “Educational Psychology: A Cognitive View.”
Bruner, Jerome S. 2009. The Process of Education. Harvard university press.
Bruner, Jerome Seymour. 1974. Toward a Theory of Instruction. Harvard: Harvard university press.
Budyastuti, Yuni, and Endang Fauziati. 2021. “Penerapan Teori Konstruktivisme Pada Pembelajaran Daring Interaktif.” Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar 3(2): 112–19.
Gagné, Robert Mills. 1985. The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: Rinehart and Winston.
Habsy, Bakhrudin All, Jerry Sheva Christian, Syifa’ul Ummah Salsabila Putri M, and Unaisah Unaisah. 2023. “Memahami Teori Pembelajaran Kognitif Dan Konstruktivisme Serta Penerapannya.” TSAQOFAH 4(1): 308–25. doi:10.58578/tsaqofah.v4i1.2177.
Lichtenstein, P E. 1977. “NEISSER, ULRICH” Cognition and Reality: Principles and Implications of Cognitive Psychology”(Book Review).” The Psychological Record 27: 636–636.
Nasution, Fauziah. 2011. Psikologi Umum: Buku Panduan Untuk Fakultas Tarbiyah. Medan: UINSU.
Nurdiyanto, Nurdiyanto, Abdul Muchlis, Ahmad Tauviqillah, Tarsono Tarsono, and Hasbiyallah Hasbiyallah. 2023. “Teori Belajar Kognitif Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.” JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6(11): 8809–19. doi:10.54371/jiip.v6i11.2609.
Nurhadi, Nurhadi. 2020. “Teori Kognitivisme Serta Aplikasinya Dalam Pembelajaran.” Edisi 2(1): 77–95. doi:10.36088/edisi.v2i1.786.
Pahru, Syaipul, Munawir Gazali, Made Ayu Pransisca, Ahmad Dedi Marzuki, and Nopi Nurpitasari. 2023. “TEORI BELAJAR KOGNITIVISTIK DAN IMPLIKASINYA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR.” NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan 4(4): 1070–77. doi:10.55681/nusra.v4i4.1745.
Pane, Aprida, and Muhammad Darwis Dasopang. 2017. “Belajar Dan Pembelajaran.” Fitrah: Jurnal kajian ilmu-ilmu keislaman 3(2): 333–52.
Piaget, Jean. 2013. Principles of Genetic Epistemology: Selected Works Vol 7. London: Routledge.
Ritonga, Y, and R R Wandini. 2023. “Penerapan Teori Belajar Kognitif Dalam Pembelajaran Matematika Di UPT SD Negeri No 060909.” Jurnal Pendidikan Tambusai 7(3): 29898–902.
Soemanto, Wasty. 2003. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Suharti, Mimi. 2011. Perkembangan Peserta Didik. Padang: IAIN IB Pres Padang.
Vygotsky, Lev S. 1978. 86 Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard: Harvard university press.
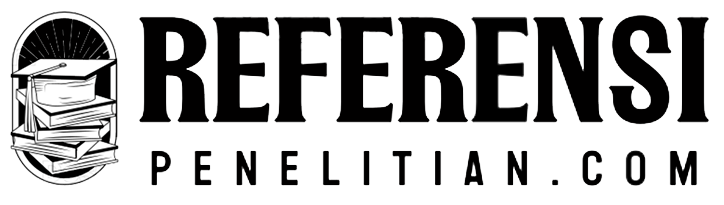

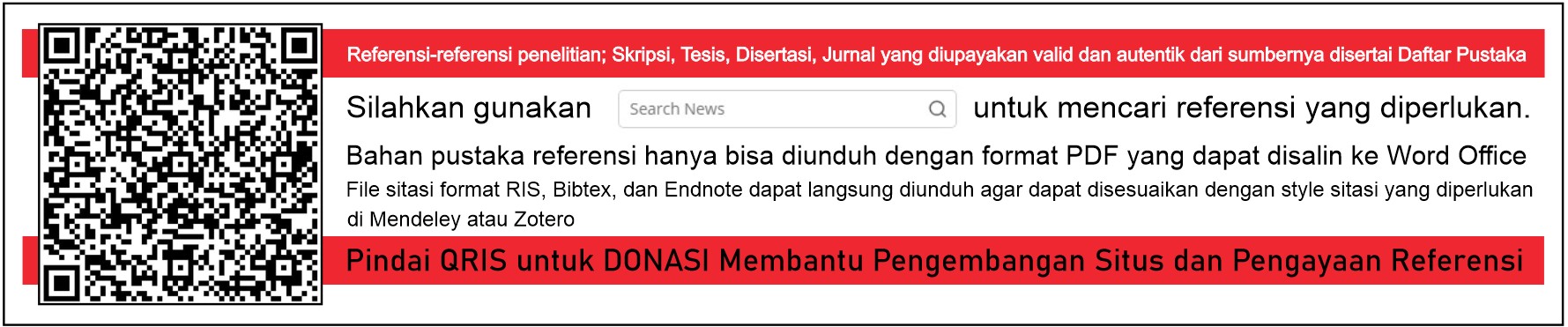
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.info/register-person?ref=IXBIAFVY
legal weed delivery online secure checkout
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/ro/register?ref=HX1JLA6Z
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Claim 5% Rebate and Exclusive Bonuses on AsterDEX https://is.gd/CGTnqR
Hello https://is.gd/tvHMGJ
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!