Bintoro (dalam Wasistiono, 2006:8) yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.
Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, menurut Suhartono dalam Wasistono (2006 : 13) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi.
dilihat pengertian desa dari pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Bouman (Beratha,1982:26) yang mendefinisikan desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.
Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003: 3)
Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat (Rahadjo, 1999 : 29)
R. Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur–unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah
N. Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam
Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menjalankan rumah tangga sendiri (Unang Sunardjo dalam Amin Suprihatini, 2007:3).
Sintesis :
Desa dapat dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat yang hidup menetap dalam suatu wilayah tertentu di luar kawasan perkotaan. Keberadaan desa merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungan fisiknya, sehingga membentuk suatu tatanan kehidupan yang khas, baik secara sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam kehidupan desa, ikatan kekeluargaan dan keterikatan sosial masih sangat kuat, ditandai oleh adanya hubungan antar warga yang saling mengenal dan saling bergantung, terutama dalam kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, atau usaha berbasis alam lainnya. Kehidupan masyarakat desa juga sangat dipengaruhi oleh tradisi, nilai-nilai adat, dan hukum adat yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Desa tidak hanya dipahami sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai komunitas hukum yang memiliki hak asal-usul, otonomi lokal, dan kemandirian dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Selain itu, desa mencerminkan keberagaman bentuk kehidupan sosial yang berakar pada budaya lokal dan mengedepankan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, desa merupakan entitas sosial yang menyatu dengan lingkungannya dan berkembang berdasarkan interaksi yang seimbang antara manusia, alam, dan budaya.
Karakteristik Masyarakat Desa
Masyarakat desa itu sendiri mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren mereka menggambarkan karakteristik masyarakat desa sebagai berikut (Jefta Leibo, 1995:7):
- Besarnya peranan kelompok primer
- Faktor geografis menentukan dasar pembentukan kelompok atau asosiasi
- Hubungan lebih bersifat akrab dan langgeng
- Homogen
- Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
- Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar
Pembagian Desa
Pembagian desa sebagai berikut (Jefta Leibo, 1994 : 18) :
- Desa Pertanian; pada jenis desa ini semua kegiatan masyarakatnya terlibat dalam bidang pertanian
- Desa Industri; pada jenis desa ini pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih banyak bergantung pada sektor industri baik industri kecil maupun industri besar.
- Desa Nelayan atau Desa Pantai; pada jenis desa ini pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakatnya bersumber pada usaha-usaha di bidang perikanan baik perikanan laut, pantai, maupun darat.
- Desa Pariwisata; pada jenis desa ini terdapat obyek wisata seperti peninggalan-peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, dan juga terdapat keindahan alam
Menurut P.H Landis membagi menjadi empat pola pemukiman penduduk yaitu (Rahardjo, 2010 : 98-99) :
- The Farm Village Type (FVT); pola pemukiman ini biasanya para keluarga petani atau penduduk tinggal bersama-sama dan berdekatan di suatu tempat dengan lahan pertanian berada di luar lokasi pemukiman.
- The Nebulous Farm Type (NFT); pola ini hampir sama dengan pola FVT bedanya di samping ada yang tinggal bersama di suatu tempat terdapat penduduk yang tinggal tersebar di luar pemukiman itu, lahan pertanian juga berada di luar pemukiman itu.
- The Arranged Isolated Farm Type (AIFT); pola pemukiman ini dimana penduduknya tinggal di sekitar jalan dan masing-masing berada di lahan pertanian mereka dengan suatu trade center di antara mereka.
- The Pure Isolated Farm Type (PIFT); pola pemukiman ini penduduknya tinggal dalam lahan pertanian mereka masing-masing terpisah dan berjauhan satu sama lain dengan suatu trade center.
Sintesis :
Desa dapat diklasifikasikan berdasarkan dominasi kegiatan ekonomi masyarakatnya maupun pola pemukimannya. Berdasarkan jenis kegiatan ekonomi, desa terbagi ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, desa pertanian, yaitu desa yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kedua, desa industri, di mana sumber utama penghasilan masyarakat berasal dari aktivitas industri, baik skala kecil maupun besar. Ketiga, desa nelayan atau desa pantai, yang menjadikan perikanan sebagai pusat kegiatan ekonomi, baik di laut, pantai, maupun perairan darat. Keempat, desa pariwisata, yaitu desa yang memiliki daya tarik wisata seperti peninggalan sejarah, keunikan budaya lokal, atau keindahan alam yang menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Sementara itu, dari sudut pandang pola pemukiman, desa dapat dibedakan berdasarkan sebaran tempat tinggal penduduk dan keterkaitannya dengan lahan pertanian. Pola Farm Village Type (FVT) menunjukkan pemukiman yang terkonsentrasi di satu lokasi, dengan lahan pertanian terletak di luar pemukiman. Pola Nebulous Farm Type (NFT) hampir serupa, namun dengan sebagian penduduk tinggal tersebar di luar pusat desa. Pola Arranged Isolated Farm Type (AIFT) memperlihatkan rumah-rumah yang berderet mengikuti jalur jalan, masing-masing berada di lahan pertanian sendiri, dengan pusat perdagangan berada di tengah. Sedangkan pola Pure Isolated Farm Type (PIFT) ditandai oleh tempat tinggal penduduk yang tersebar berjauhan satu sama lain di tengah lahan pertanian masing-masing, tetap terhubung dengan sebuah pusat perdagangan.
Klasifikasi ini menunjukkan bahwa desa memiliki keragaman karakteristik baik dari segi aktivitas ekonomi maupun struktur ruangnya, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat.
Daftar Pustaka (APSA) :
Adisasmita, Rahardjo. 2013. Pembangunan Perdesaan pendekatan Partisipatif, Tipologi, Starategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Jakarta: Graha Ilmu.
Beratha, I. Nyoman. 1982. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bintarto, Redi. 2010. Desa Kota. Bandung: Alumni.
Daldjoeni, Nathanael. 2011. Interaksi Desa-Kota. Jakarta: Rineka Cipta.
Leibo, Jefta. 1994. Sosiologi Pedesaan Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Berparadigma Ganda. Yogyakarta: Andi Offset.
Raharjo, Rudianto. 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
Widjaja, H.A.W. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. Jakarta: Rajawali Press.
Unduh PDF disini
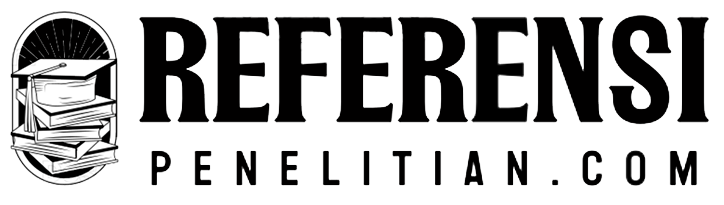

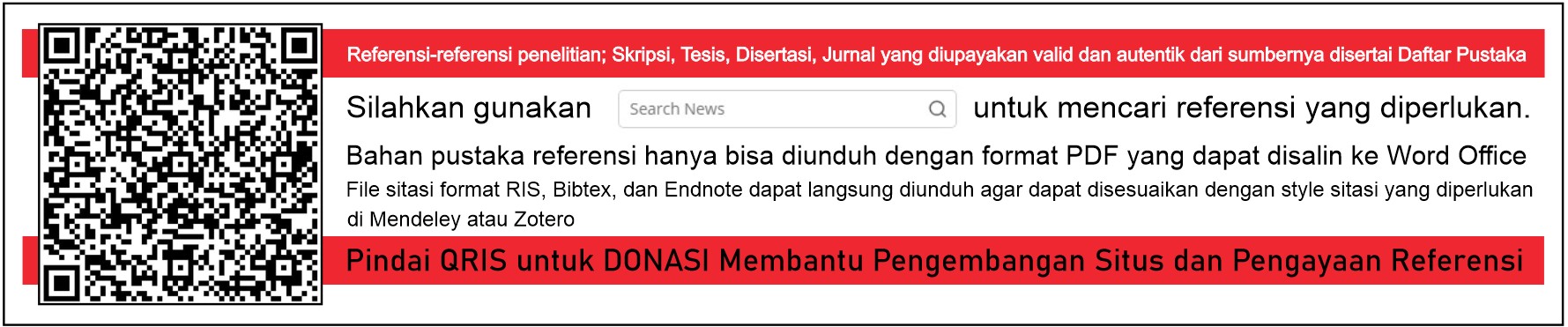
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/ro/register-person?ref=HX1JLA6Z
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.info/ES_la/register?ref=VDVEQ78S
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.info/lv/register?ref=SMUBFN5I
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.info/zh-CN/register-person?ref=WFZUU6SI
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.info/sk/register-person?ref=WKAGBF7Y