Latar Belakang
Indonesia merupakan bangsa multikultural yang memiliki keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang sangat kompleks. Keanekaragaman ini, sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf Perdana, Sumargono, dan Valensy Rachmedita (2019:80–84), dapat menjadi kekuatan integratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan disintegrasi jika tidak dikelola secara tepat. Kota Surakarta, misalnya, kerap menjadi lokasi kerusuhan dengan latar belakang etnis, sehingga pembelajaran sejarah dinilai penting untuk menanamkan kesadaran multikultural pada siswa.
Etmi Hardi dan Mudjiran (2022:8932–8933) memperluas pandangan ini dengan menekankan bahwa diversitas sosiokultural tidak hanya berkaitan dengan etnis dan budaya, tetapi juga mencakup gender, usia, ekonomi, dan bahasa. Pendidikan multikultural dan gender dalam kerangka Kurikulum Merdeka perlu dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, agar guru mampu melayani kebutuhan belajar anak secara adil sesuai karakteristiknya.
Dalam perspektif teori belajar, Nia Indah Purnamasari (2019:239–241) mengaitkan konsep sosiokulturalisme Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif, dengan pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Interaksi sosial tidak hanya membentuk aspek kognitif, tetapi juga harus diarahkan untuk pembinaan moral dan spiritual.
Julia Rahmawati dan Septiyati Purwandari (2021:329–331) mengingatkan bahwa arus globalisasi dan modernisasi telah mengikis identitas bangsa, khususnya pada anak usia sekolah dasar. Fenomena lunturnya nilai gotong royong, meningkatnya individualisme, serta ketergantungan pada teknologi mengharuskan adanya pendidikan karakter berbasis sosiokultural agar anak tetap menjunjung tinggi norma dan moral masyarakat.
Asri Andika Amalia dan Raisya Miftakhul Rahma (2022:276–279), menempatkan keluarga sebagai institusi pendidikan pertama dalam membentuk kepribadian anak. Melalui keteladanan, nasehat, serta pembiasaan sesuai syariat Islam, keluarga dapat menginternalisasikan nilai sosiokultural berupa tolong-menolong, persatuan, dan persaudaraan.
Sementara itu, dalam ranah pembelajaran bahasa, Richa Dwi Rahmawati (2019:9–11) menegaskan bahwa bahasa merupakan bagian integral dari budaya yang sarat dengan nilai sosiokultural. Pembelajaran bahasa berbasis sosiokultural tidak hanya meningkatkan keterampilan komunikasi, tetapi juga menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, sekaligus menanggapi tantangan globalisasi yang membawa pengaruh bahasa asing.
Keanekaragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa di Indonesia menjadikan bangsa ini sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Namun, kemajemukan tersebut seringkali melahirkan potensi konflik sosial. Yusuf Perdana, Sumargono, dan Valensy Rachmedita (2019:80–83) menegaskan bahwa Kota Surakarta merupakan contoh nyata bagaimana diversitas sosial dapat memicu kerusuhan, mulai dari Geger Pecinan 1742 hingga peristiwa Mei 1998. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural melalui pembelajaran sejarah dipandang sebagai solusi preventif yang efektif untuk menanamkan nilai toleransi dan kesadaran kebangsaan pada generasi muda.
Etmi Hardi dan Mudjiran (2022:8932–8934) menyatakan bahwa diversitas sosiokultural tidak hanya terlihat dari etnis dan budaya, tetapi juga mencakup perbedaan gender, ekonomi, dan bahasa. Apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dan gender perlu diintegrasikan dalam kurikulum, khususnya melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik secara adil dan inklusif.
Dalam tataran teori, Nia Indah Purnamasari (2019:239–241) menekankan pentingnya pendekatan sosiokultural Vygotsky yang melihat bahwa perkembangan kognitif siswa sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Namun, perspektif pendidikan Islam menambahkan dimensi transendental dengan menekankan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Artinya, pendidikan tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kemampuan intelektual, tetapi juga untuk pembinaan moral dan spiritual yang berakar pada nilai-nilai keagamaan.
Kondisi globalisasi semakin memperkuat urgensi pendidikan berbasis sosiokultural. Julia Rahmawati dan Septiyati Purwandari (2021:329–331) menemukan bahwa modernisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan lunturnya jati diri bangsa, terutama pada anak usia sekolah dasar. Perilaku individualistik, kurangnya sopan santun, serta ketergantungan terhadap gawai menjadi tantangan serius yang harus diatasi melalui penguatan pendidikan karakter berbasis sosiokultural di sekolah.
Dalam lingkup keluarga, Asri Andika Amalia dan Raisya Miftakhul Rahma (2022:276–278) menjelaskan bahwa keluarga merupakan institusi pendidikan pertama yang sangat menentukan pembentukan kepribadian anak. Nilai sosiokultural seperti tolong-menolong, persatuan, dan persaudaraan harus ditanamkan melalui keteladanan, nasehat, dan pembiasaan sesuai syariat Islam. Dengan demikian, keluarga menjadi benteng utama dalam menghadapi pengaruh budaya global yang berpotensi mengikis identitas religius dan moral generasi muda.
Di sisi lain, pembelajaran bahasa juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosiokultural. Richa Dwi Rahmawati (2019:9–11) mengungkapkan bahwa bahasa merupakan bagian integral dari budaya dan sarana utama komunikasi antar manusia. Dalam masyarakat plural, pembelajaran bahasa berbasis sosiokultural menjadi penting untuk menanamkan sikap saling menghormati dan toleransi. Integrasi nilai multikultural dalam pembelajaran bahasa sekaligus dapat memberdayakan kelompok minoritas dan memperkaya kurikulum pendidikan nasional.
Fenomena
Yusuf Perdana dkk. (2019) mencatat bahwa Kota Surakarta mengalami lima kali kerusuhan besar sejak abad ke-18, mulai dari Geger Pecinan (1742) hingga kerusuhan Mei 1998. Fakta ini menunjukkan bahwa perbedaan etnis kerap menjadi pemicu disintegrasi. Untuk itu, pembelajaran sejarah dipandang sebagai media efektif dalam menanamkan kesadaran multikultural kepada siswa.
Etmi Hardi dan Mudjiran (2022) mencatat konflik horizontal di Indonesia, seperti kerusuhan Mei 1998 yang menelan sekitar 2.000 korban jiwa, konflik agama di Maluku (1999–2003), dan konflik Dayak–Madura (2000), menjadi pelajaran berharga bagi pendidikan multikultural. Mereka menilai Kurikulum Merdeka harus memberi ruang pada pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan belajar setiap siswa terpenuhi sesuai latar sosial budayanya.
Landasan Teori
Landasan teori menjadi pijakan penting dalam penelitian untuk memberikan kerangka konseptual. Keenam artikel yang dikaji menggunakan teori-teori sosial, budaya, pendidikan, dan bahasa yang relevan dengan konteks sosiokultural.
- Teori Pendidikan Multikultural (Banks, 2004:12) → pendidikan harus menanamkan kesadaran keberagaman budaya.
- Teori Integrasi Sosial (Durkheim, 1997:45) → nilai-nilai multikultural dapat mencegah konflik etnis dan menjaga harmoni sosial.
- Teori Pendidikan Multikultural (Nieto, 2002:34) → menekankan kesetaraan hak belajar dalam masyarakat yang heterogen.
- Teori Gender dalam Pendidikan (Connell, 2009:17) → pendidikan harus responsif terhadap kesetaraan gender.
- Teori Pembelajaran Berdiferensiasi (Tomlinson, 2014:56) → guru menyesuaikan strategi belajar dengan karakteristik siswa.
- Teori Sosiokultural Vygotsky (1978:86) → perkembangan kognitif ditentukan interaksi sosial, konsep Zone of Proximal Development (ZPD) dan scaffolding.
- Teori Pendidikan Islam (Al-Attas, 1980:22; Nahlawi, 1995:103) → menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, moral, spiritual, dan ukhrawi.
- Teori Pendidikan Karakter (Lickona, 1991:51) → pembentukan moral, tanggung jawab, dan etika.
- Teori Sosiokultural dalam Pendidikan (Tilaar, 2002:41) → pendidikan dan budaya tidak dapat dipisahkan.
- Teori Pendidikan Keluarga (Musmualim & Miftah, 2016:77) → keluarga sebagai institusi pertama pembentuk karakter.
- Teori Pendidikan Islam Sosio-Kultural (Nahlawi, 1995:111) → keluarga Muslim menanamkan nilai sosial, moral, dan religius melalui keteladanan dan pembiasaan.
- Teori Sosiolinguistik (Fishman, 1972:14) → bahasa adalah bagian dari budaya dan masyarakat.
- Teori Sosiokultural Vygotsky (1978:92) → bahasa sebagai hasil interaksi sosial dan akulturasi budaya.
Tinjauan Pustaka
Kajian mengenai pendidikan berbasis sosiokultural telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam perspektif multikultural, karakter, keluarga, maupun bahasa. Beberapa penelitian relevan dapat diuraikan sebagai berikut:
- Pendidikan multikultural dan sejarah
Banks (2004:12) menekankan bahwa pendidikan multikultural merupakan sarana untuk membangun kesadaran akan keberagaman budaya dalam masyarakat majemuk. Hal ini sejalan dengan Mahfud (2010:77) yang menunjukkan bahwa integrasi multikultural dalam pembelajaran sejarah mampu mengurangi stereotip etnis pada siswa. Senada dengan itu, Yusuf Perdana, Sumargono, dan Valensy Rachmedita (2019:80–84) menyoroti pembelajaran sejarah sebagai media integrasi sosiokultural dengan menelaah dinamika konflik etnis di Surakarta.
- Diversitas sosiokultural dan gender
Nieto (2002:34) menjelaskan pentingnya pendidikan multikultural untuk mewujudkan kesetaraan sosial dalam pendidikan, sedangkan Connell (2009:17) menegaskan perlunya integrasi perspektif gender agar sekolah lebih inklusif. Penelitian Etmi Hardi dan Mudjiran (2022:8932–8934) memperkuat temuan tersebut dengan menekankan pembelajaran berdiferensiasi sebagai strategi mengakomodasi keragaman sosial dan gender, meski penelitian ini terbatas pada praktik kelas dan tidak menyinggung ranah kebijakan.
- Perspektif sosiokultural Barat dan Islam
Vygotsky (1978:86) menegaskan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi interaksi sosial melalui konsep Zone of Proximal Development (ZPD). Di sisi lain, Al-Attas (1980:22) menekankan pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk manusia seutuhnya, mencakup aspek kognitif, moral, dan spiritual. Nia Indah Purnamasari (2019:239–241) kemudian mengomparasikan kedua perspektif ini, meski kajiannya masih bersifat konseptual dan terbatas pada studi literatur.
- Pendidikan karakter berbasis sosiokultural
Lickona (1991:51) menegaskan pentingnya pendidikan karakter dalam menanamkan nilai moral sejak dini, sedangkan Tilaar (2002:41) menambahkan bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari dimensi budaya bangsa. Julia Rahmawati dan Septiyati Purwandari (2021:329–331) mengaplikasikan teori tersebut dalam pembelajaran di SD Muhammadiyah Donorejo dengan menekankan internalisasi nilai-nilai karakter berbasis budaya lokal, meski penelitian ini terbatas pada satu sekolah.
- Pendidikan sosio-kultural dalam keluarga
Nahlawi (1995:111) menyebutkan bahwa keluarga merupakan pusat pendidikan utama dalam Islam yang menanamkan nilai moral dan spiritual melalui teladan. Musmualim & Miftah (2016:77) menunjukkan bahwa sekitar 70% nilai keagamaan anak terbentuk melalui pendidikan keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asri Andika Amalia dan Raisya Miftakhul Rahma (2022:276–279) yang menegaskan peran dominan keluarga Muslim dalam menanamkan nilai tolong-menolong, persatuan, dan persaudaraan, meski ruang lingkupnya terbatas pada ranah keluarga.
- Pembelajaran bahasa berbasis sosiokultural
Fishman (1972:14) dalam kajian sosiolinguistik menegaskan bahwa bahasa tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial budaya. Kramsch (1998:3) juga menekankan bahwa pembelajaran bahasa sekaligus berarti pembelajaran budaya. Richa Dwi Rahmawati (2019:9–11) mengembangkan gagasan ini dengan menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan 718 bahasa daerah merupakan laboratorium sosial yang kaya untuk menumbuhkan toleransi dan multikulturalisme melalui pembelajaran bahasa, meski penelitiannya lebih menyoroti aspek budaya daripada keterampilan bahasa secara teknis.
- Dampak globalisasi dan digitalisasi
Perubahan sosial akibat globalisasi juga turut memengaruhi pendidikan sosiokultural. Julia Rahmawati dan Septiyati Purwandari (2021) mencatat bahwa pada 2020 sekitar 64% penduduk Indonesia menggunakan internet, dengan 59% di antaranya aktif di media sosial dan rata-rata penggunaan hampir delapan jam per hari. Kondisi ini menjadikan anak-anak usia sekolah dasar rentan terhadap penurunan moral, sehingga pendidikan karakter berbasis sosiokultural menjadi semakin mendesak.
Sintesis :
Kajian mengenai pendidikan berbasis sosiokultural menunjukkan bahwa tema ini telah dibahas dari berbagai perspektif, mulai dari multikultural, karakter, keluarga, bahasa, hingga dampak globalisasi. Pendidikan multikultural dipandang sebagai sarana untuk membangun kesadaran keberagaman dalam masyarakat majemuk serta mengurangi stereotip melalui integrasi nilai-nilai dalam pembelajaran sejarah. Dari sisi diversitas sosial dan gender, pendidikan multikultural menekankan pentingnya kesetaraan dan inklusivitas, salah satunya melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengakomodasi keragaman siswa.
Perspektif sosiokultural juga hadir dalam perbandingan antara teori Barat dan Islam. Jika pendekatan Barat menekankan interaksi sosial sebagai pendorong perkembangan kognitif, maka perspektif Islam menambahkan dimensi moral dan spiritual, sehingga pendidikan tidak hanya bersifat intelektual tetapi juga membentuk manusia secara utuh. Dalam ranah pendidikan karakter, integrasi nilai budaya dipandang esensial sejak dini, dengan pembelajaran yang diarahkan pada internalisasi nilai moral, sosial, dan kebangsaan melalui konteks lokal.
Keluarga menempati posisi utama sebagai agen pendidikan sosiokultural, karena menjadi lingkungan pertama dalam menanamkan nilai moral, keagamaan, serta sikap tolong-menolong dan persaudaraan. Di samping itu, bahasa dipahami bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga media untuk menumbuhkan toleransi dan multikulturalisme, khususnya di Indonesia yang memiliki keragaman bahasa daerah sebagai kekayaan budaya.
Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, pendidikan sosiokultural menghadapi tantangan baru. Tingginya penggunaan internet dan media sosial di kalangan anak-anak menjadikan mereka rentan terhadap penurunan moral. Oleh karena itu, pendidikan berbasis sosiokultural semakin mendesak untuk dikembangkan sebagai strategi menanamkan nilai karakter, moral, dan kebudayaan di tengah arus perubahan sosial yang cepat.
Daftar Pustaka
Al-Attas, Muhammad Naquib. 1980. The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia Kuala Lumpur.
Al-Nahlawi, Abdurrahman. 1995. Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Masyarakat. Jakarta: Gema Insani.
Amalia, Asri Andika, and Raisya Miftakhul Rahma. 2022. “Aspek-Aspek Pengembangan Pendidikan Sosio-Kultural Dalam Keluarga Muslim.” El-Tarbawi 15(2):275–304. doi:10.20885/tarbawi.vol15.iss2.art6.
Banks, James A. 1993. “Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice.” Review of Research in Education 19:3–3. doi:10.2307/1167339.
Connell, Raewyn. 2009. Gender in Education: An Overview. Westport: Preager Publisher.
Durkheim, Emile. 2023. “The Division of Labour in Society.” Pp. 15–34 in Social theory re-wired. London: Routledge.
Fishman, Johua A. 1971. The Sociology of Language. Paris: Mouton.
Hardi, Etmi, and Mudjiran Mudjiran. 2022. “Diversitas Sosiokultural Dalam Wujud Pendidikan Multikultural, Gender Dan Pembelajaran Berdiferensiasi.” Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 4(6):8931–42.
Kramsch, Claire. 2014. “Language and Culture.” AILA Review 27(1):30–55.
Lickona, Thomas. 1992. Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam.
Mahfud, Choirul. 2010. Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
Nieto, Sonia. 2001. Language, Culture, and Teaching: Critical Perspectives. London: Routledge.
Purnamasari, Nia Indah. 2019. “Komparasi Konsep Sosiokulturalisme Dalam Pendidikan: Perspektif Barat Dan Islam.” EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam 9(2):238–61. doi:10.54180/elbanat.2019.9.2.238-261.
Rahmawati, Julia, and Septiyati Purwandari. 2021. “Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Sosiokultural Pada Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Donorejo.” Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan 6(3):329–35. doi:10.29303/jipp.v6i3.211.
Rahmawati, Richa Dwi. 2019. “PEMBELAJARAN BAHASA BERBASIS SOSIOKULTURAL.” 5(1):9–13.
Tilaar, Henry Alexis Rudolf. 2002. Perubahan Sosial Dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
Tomlinson, Carol Ann. 2014. The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. New York: Ascd.
Vygotsky, Lev S. 1978. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Vol. 86. Harvard: Harvard university press.
Yusuf Perdana, Sumargono Sumargono, and Valensy Rachmedita. 2019. “Integrasi Sosiokultural Siswa Dalam Pendidikan Multikultural Melalui Pembelajaran Sejarah.” Jurnal Pendidikan Sejarah 8(2):79–98. doi:10.21009/JPS.082.01.
download pdf disini
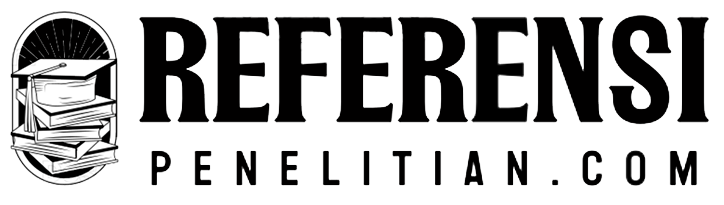

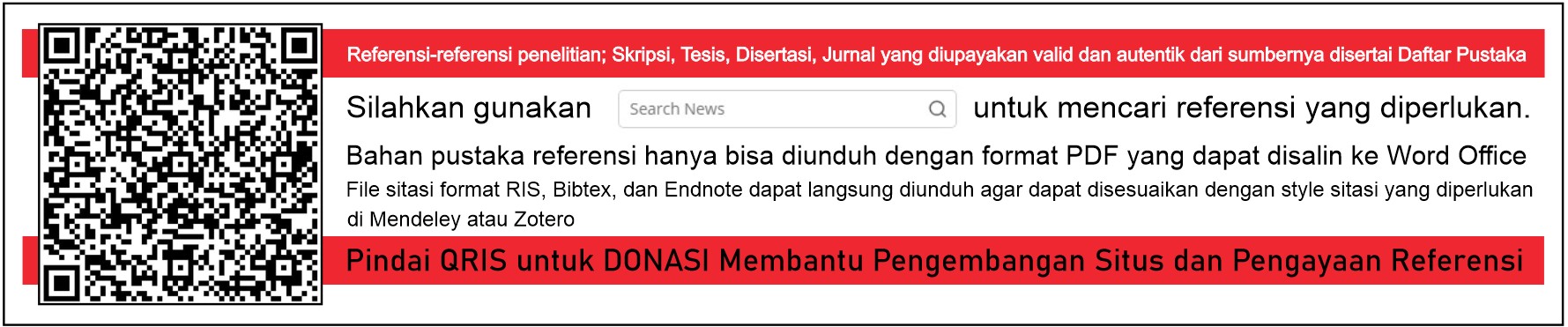
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/register?ref=IHJUI7TF