Latar Belakang
Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Peningkatan mutu pendidikan menuntut adanya perubahan paradigma pembelajaran yang lebih menekankan pada interaksi manusiawi antara pendidik dan peserta didik. Teori konstruktivisme muncul sebagai salah satu pendekatan penting yang menekankan bahwa peserta didik membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman dan pemikiran. Paradigma lama yang bersifat pasif dan satu arah dianggap tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan globalisasi (Suparlan, 2019:80-81).
Munculnya teori konstruktivisme sosial, yang dipengaruhi oleh Vygotsky dan Piaget, memberikan dasar penting bagi pembelajaran di era digital. Pengetahuan dipandang sebagai hasil interaksi sosial dan pengalaman belajar peserta didik. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), pendekatan konstruktivisme dinilai lebih relevan untuk membangkitkan partisipasi aktif, menumbuhkan kemandirian, dan meningkatkan kebermaknaan belajar. Namun, praktik pendidikan di sekolah masih cenderung bersifat tradisional sehingga peserta didik kurang menyukai materi PAI. Oleh karena itu, integrasi konstruktivisme dengan teknologi digital menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan kebermaknaan pembelajaran (Saidah, 2021:164-166).
Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, namun dalam praktiknya pembelajaran di Indonesia masih lemah dan cenderung bersifat konvensional. Guru sering kali dominan menggunakan metode ceramah sehingga siswa pasif, jenuh, dan tidak terdorong untuk berpikir kritis. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan pendekatan konstruktivisme yang memberi ruang bagi peserta didik menggali pengetahuan melalui pengalaman. Agar lebih efektif, pendekatan ini dimodifikasi dengan strategi “tugas dan paksa” untuk menanamkan tanggung jawab belajar serta mengurangi sikap menunda dalam menyelesaikan tugas (Maulana & Leonard, 2018:405-406).
Konstruktivisme memandang pengetahuan sebagai hasil konstruksi individu melalui pengalaman dan interaksi sosial (Piaget & Vygotsky). Prinsip konstruktivistik menekankan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Namun, praktik pendidikan di Indonesia masih didominasi pendekatan konvensional yang berpusat pada guru, sehingga daya serap siswa rendah. Data internasional seperti TIMSS (2003) dan PISA (2006) menunjukkan rendahnya prestasi siswa Indonesia, menegaskan perlunya implementasi pedagogi konstruktivisme secara lebih konsisten dalam kurikulum dan praktik pembelajaran (Nurhidayati, 2017:2-3).
Fenomena
Paradigma pembelajaran di sekolah masih banyak menggunakan cara tradisional yang berorientasi pada transfer pengetahuan, sehingga siswa cenderung pasif. Kondisi ini bertolak belakang dengan tuntutan zaman globalisasi yang menekankan kemandirian berpikir dan kreativitas peserta didik. Kurangnya penerapan teori konstruktivisme menyebabkan proses belajar mengajar tidak sepenuhnya mendorong siswa untuk membangun pengetahuan secara mandiri (Suparlan, 2019:81-82).
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) masih kurang diminati oleh peserta didik karena dianggap monoton dan tidak relevan dengan konteks kehidupan digital mereka. Guru masih dominan sebagai pusat pembelajaran, sehingga siswa kurang aktif dan kebermaknaan belajar tidak tercapai. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran berbasis konstruktivisme belum dioptimalkan (Saidah, 2021:165-166).
Masalah utama dalam pendidikan di Indonesia adalah lemahnya proses pembelajaran, di mana siswa tidak terdorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan aktif. Guru masih banyak menggunakan metode ceramah tradisional yang membuat siswa pasif, bosan, dan hanya berorientasi pada hasil kognitif. Akibatnya, siswa kurang mandiri, sering menunda tugas, dan tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses belajarnya (Maulana & Leonard, 2018:405-406).
Konsep konstruktivisme sebenarnya sudah tertuang dalam kurikulum, namun dalam praktik pembelajaran di sekolah masih didominasi pendekatan konvensional yang berpusat pada guru. Akibatnya, daya serap siswa rendah dan prestasi belajar Indonesia secara internasional (TIMSS, PISA) masih tergolong rendah. Rendahnya implementasi pedagogi konstruktivisme menyebabkan siswa kurang diberi ruang untuk membangun pengetahuan secara mandiri (Nurhidayati, 2017:3-4).
Tinjauan Teori
Teori konstruktivisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan tidak diberikan secara pasif, melainkan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Menurut Piaget, konstruktivisme menekankan proses asimilasi dan akomodasi untuk membentuk skema pengetahuan baru, sedangkan Vygotsky menambahkan dimensi sosial melalui konsep zone of proximal development (ZPD). Dalam pembelajaran, konstruktivisme menempatkan guru sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri (Suparlan, 2019:81-82).
Teori konstruktivisme sosial Vygotsky dan konstruktivisme kognitif Piaget. Vygotsky menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman kolektif, sementara Piaget memandang bahwa setiap individu mengonstruksi makna melalui interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran konstruktivis dalam era digital menekankan partisipasi aktif siswa, kebermaknaan belajar, serta integrasi teknologi sebagai sarana membangun pengetahuan baru (Saidah, 2021:164-165).
Teori belajar konstruktivistik, di mana peserta didik berperan aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar. Guru bertugas sebagai fasilitator yang membimbing siswa menggali ilmu pengetahuan sendiri. Untuk memperkuat tanggung jawab belajar siswa, konstruktivisme ini dimodifikasi dengan strategi tugas dan paksa, yaitu pemberian tugas yang disertai dorongan (motivasi atau sedikit tekanan) agar siswa menyelesaikan tepat waktu, sehingga meningkatkan disiplin dan kemandirian (Maulana & Leonard, 2018:405-406).
Berlandaskan pada filsafat pengetahuan konstruktivisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Glasersfeld, Piaget, dan Vygotsky :
- Piaget menekankan konstruktivisme kognitif: belajar adalah proses individu membangun skema pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan.
- Vygotsky menekankan konstruktivisme sosial: belajar merupakan proses kolaboratif yang terbentuk melalui interaksi dengan orang lain dan budaya.
- Glasersfeld menegaskan bahwa pengetahuan bukan tiruan realitas, melainkan hasil konstruksi kognitif individu (Nurhidayati, 2017:1-2).
Penelitian Terdahulu
Kajian mengenai konstruktivisme dalam pembelajaran terus berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan konvensional yang menempatkan guru sebagai pusat pengetahuan. Dalam kerangka teoritis yang ditawarkan oleh Suparlan (2019), konstruktivisme dipahami sebagai teori belajar yang menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui proses kognitif (Piaget) maupun interaksi sosial (Vygotsky). Piaget menekankan proses asimilasi dan akomodasi dalam membentuk skema kognitif, sementara Vygotsky menyoroti pentingnya Zone of Proximal Development (ZPD) dan interaksi sosial sebagai elemen penting dalam proses belajar. Implikasinya, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, bukan sebagai pusat pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sendiri (Suparlan, 2019:81-82).
Lebih lanjut, Zahrotus Saidah (2021) menegaskan relevansi konstruktivisme dalam konteks pendidikan digital. Ia menggabungkan perspektif konstruktivisme sosial Vygotsky dan konstruktivisme kognitif Piaget, sambil menggarisbawahi bahwa kemajuan teknologi digital memperluas ruang interaksi sosial yang memungkinkan konstruksi pengetahuan menjadi lebih dinamis. Dalam pandangan ini, guru bertindak sebagai mediator yang membantu siswa menavigasi informasi, bukan sebagai sumber tunggal pengetahuan. Implementasi model ini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), misalnya, dianggap dapat meningkatkan kebermaknaan belajar karena mampu menghadirkan konteks yang lebih relevan dan partisipatif (Saidah, 2021:164–166).
Dalam konteks strategi pembelajaran, Ichwan Maulana dan Leonard (2018) menawarkan pendekatan konstruktivisme yang dikombinasikan dengan strategi Tugas dan Paksa. Strategi ini dikembangkan sebagai respons terhadap kelemahan metode ceramah yang menjadikan siswa pasif. Dengan memberi tugas yang terstruktur dan wajib diselesaikan, siswa diarahkan untuk membangun pengetahuan secara aktif melalui keterlibatan langsung dalam proses belajar. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian belajar, sekaligus memperkuat prinsip-prinsip konstruktivisme yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik (Maulana & Leonard, 2018:405–406).
Sementara itu, Euis Nurhidayati (2017) mengangkat isu lebih mendasar dalam praksis pendidikan Indonesia, yakni perlunya transisi dari pedagogi konvensional ke pendidikan konstruktivistik. Berdasarkan filsafat konstruktivisme, pengetahuan bukanlah entitas yang dapat dipindahkan dari guru ke siswa, melainkan dibangun secara aktif oleh siswa sendiri. Ia menekankan empat prinsip utama: (1) pengetahuan dikonstruksi, bukan ditransfer; (2) proses belajar bersifat berkelanjutan; (3) guru hanya sebagai penyedia konteks belajar; dan (4) keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh keaktifan siswa. Oleh karena itu, Nurhidayati menegaskan pentingnya perubahan paradigma pembelajaran di Indonesia agar lebih berpusat pada siswa dan berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis serta pembelajaran bermakna (Nurhidayati, 2017:2–3).
Secara keseluruhan, keempat kajian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan konstruktivistik bukan hanya menawarkan kerangka teoritik alternatif terhadap pembelajaran, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi pedagogik yang lebih partisipatif, reflektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk di era digital saat ini.
Daftar Pustaka
Maulana, I., & Leonard. (2018). Pendekatan konstruktivisme dengan strategi pembelajaran tugas dan paksa. Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, 404–410. Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI.
Nurhidayati, E. (2017). Pedagogi konstruktivisme dalam praksis pendidikan Indonesia. Indonesian Journal of Educational Counseling, 1(1), 1–14.
Saidah, Z. (2021). Pendidikan berbasis konstruktivisme dalam meningkatkan kebermaknaan belajar di era digital. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 7(2), 163–175.
Suparlan. (2019). Teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, 1(2), 79–88.
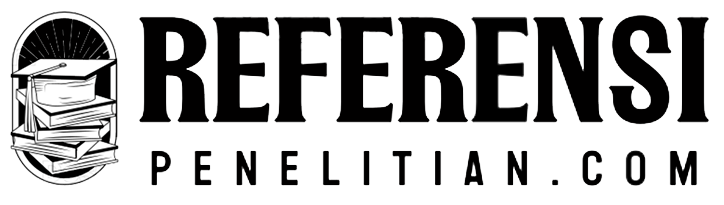

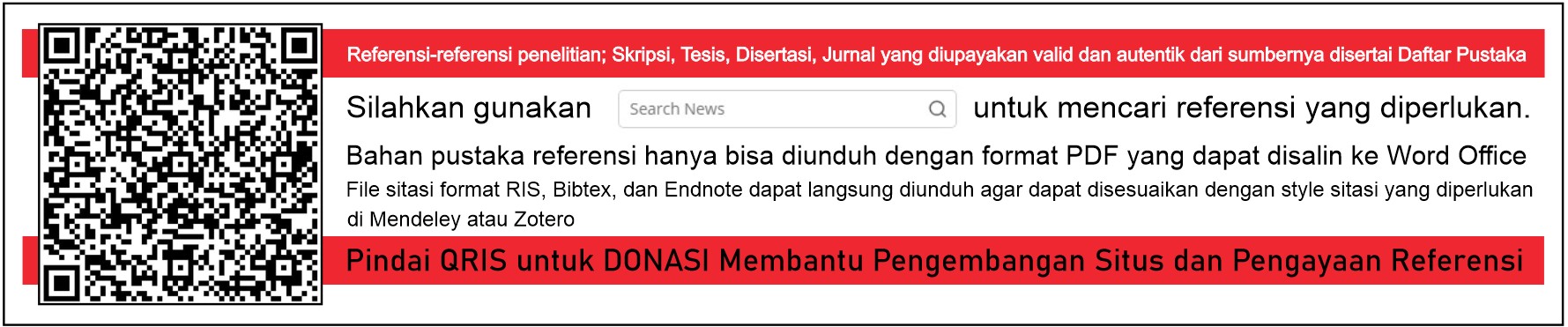
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/cs/register-person?ref=OMM3XK51
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/ka-GE/register?ref=ILE8IH9H
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.