Berikut beberapa fenomena dan permasalahan terkait implementasi kebijakan publik dalam berbagai bidang yang dapat menjadi bahan untuk latar belakang penelitian tentang implementasi kebijakan publik :
Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga penanganan bencana. Sejak lama, kebijakan publik dipahami sebagai sarana pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, tetapi tantangan terbesar terletak pada tahap implementasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi terutama pada konsistensi, kapasitas, dan komitmen dalam pelaksanaannya.
Gulo, Mendrofa, dan Elazhari (2024, hlm. 388-389) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan selalu terkait dengan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan publik di tingkat desa, misalnya, seringkai menghadapi kendala karena perbedaan kepentingan aktor dan keterbatasan kapasitas lokal. Padahal, otonomi desa seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di level nasional, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam perumusan kebijakan, mulai dari GBHN, REPELITA, hingga RUU Cipta Kerja. Namun, banyak kebijakan gagal mencapai tujuannya. Kristian (2023, hlm. 88-89) menekankan bahwa dominasi lembaga internasional, duplikasi kelembagaan, dan maladministrasi menjadi penyebab utama lemahnya implementasi. Dampaknya tidak hanya berupa pemborosan sumber daya, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kegagalan implementasi juga terlihat pada bidang pendidikan. Menurut Dwi et al., (2024, hlm. 7095-7096), kebijakan pendidikan menghadapi masalah klasik berupa ketimpangan akses, kualitas guru rendah, dan minimnya koordinasi antara pusat dan daerah. Hal ini berakibat pada rendahnya daya saing sumber daya manusia, yang pada gilirannya memengaruhi produktivitas ekonomi nasional.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi isu penting. Chairunnisa, Habibi, dan Berthanila (2023, hlm. 32-34) menemukan bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 di Kota Serang masih menghadapi kendala serius. Rendahnya komitmen pejabat publik dan kasus korupsi melemahkan upaya menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memperburuk krisis kepercayaan masyarakat.
Dalam isu lingkungan, Tay dan Rusmiwari (2019, hlm. 218-219) menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Meski terdapat regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi di lapangan belum maksimal. Tingginya pencemaran lingkungan dan pembangunan yang tidak terkendali mencerminkan lemahnya pengawasan dan koordinasi.
Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran tambahan mengenai pentingnya kebijakan yang adaptif dan responsif. Roring, Mantiri, dan Lapian (2021, hlm. 2-3) menunjukkan bahwa pemerintah desa, khususnya di Desa Ongkaw 1, berperan penting dalam mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan pandemi. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Berbagai temuan tersebut mengindikasikan bahwa problem utama kebijakan publik di Indonesia bukan terletak pada kelangkaan peraturan, melainkan pada lemahnya implementasi. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, minimnya partisipasi masyarakat, hingga kurangnya konsistensi politik menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi kebijakan publik, baik di bidang pelayanan publik, pendidikan, lingkungan, maupun penanganan krisis, menjadi penting untuk menemukan strategi perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif.
Implementasi kebijakan publik tidak hanya melibatkan instansi pelaksana, tetapi juga dipengaruhi jejaring sosial, politik, dan ekonomi. Setiap tahap implementasi—mulai dari pengesahan aturan, pelaksanaan oleh instansi, hingga penerimaan kelompok sasaran—menentukan dampak yang dihasilkan, baik diharapkan maupun tidak. Dalam konteks otonomi desa, kebijakan publik diarahkan pada kemandirian desa, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara perumusan kebijakan dengan praktik implementasi di lapangan (Gulo et al., 2024, hlm. 388-389)
Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas untuk memenuhi kebutuhan warga negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009. Dalam konteks good governance, partisipasi masyarakat menjadi indikator penting bersama transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diatur dalam PermenPANRB No. 16 Tahun 2017 bertujuan memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat. Namun, hingga tahun 2022 hanya 40,61% unit penyelenggara yang melaksanakan FKP. Rendahnya implementasi ini disebabkan keterbatasan anggaran, SDM, dan komitmen penyelenggara, sehingga diperlukan strategi baru untuk optimalisasi partisipasi publik (Rachmat et al., 2023, hlm. 2-3)
Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melahirkan banyak kebijakan publik seperti GBHN, REPELITA, hingga RUU Cipta Kerja. Namun, sebagian besar belum mampu menjawab masalah mendasar bangsa karena lemahnya implementasi. Tantangan besar yang muncul antara lain: pengaruh lembaga internasional, duplikasi kelembagaan, dan praktik maladministrasi. Kegagalan kebijakan berimplikasi pada pemborosan sumber daya, hilangnya kepercayaan rakyat, dan citra buruk Indonesia di kancah internasional (Kristian, 2023, hlm. 88-89)
Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang strategis karena berhubungan langsung dengan pembangunan manusia. Namun, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah: akses pendidikan belum merata, kualitas guru rendah, keterbatasan pendanaan, hingga lemahnya koordinasi pusat-daerah. Hal ini berimbas pada rendahnya daya saing lulusan serta stagnasi pembangunan sektor lain. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi kebijakan pendidikan dengan kebijakan publik lainnya (Dwi et al., 2024, hlm. 7095-7096)
Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 merupakan fondasi penting bagi terciptanya good governance. Melalui transparansi informasi, masyarakat dapat terlibat dalam proses kebijakan publik sekaligus mengawasi kinerja pemerintah. Namun, implementasi di daerah, termasuk di Kota Serang, seringkali tidak konsisten. Tantangan muncul dalam hal akuntabilitas pejabat publik, kasus korupsi, serta rendahnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan keterbukaan informasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah daerah (Chairunnisa et al., 2023, hlm. 32-34)
Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP tentang AMDAL dan RTRWN, implementasi di lapangan masih lemah. Tingginya pencemaran lingkungan dan pembangunan yang tidak terkendali menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan praktik. Di Desa Tlekung, Kota Batu, misalnya, pembangunan berkelanjutan masih menghadapi pro dan kontra di masyarakat (Tay & Rusmiwari, 2019, hlm. 218-219)
Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah desa untuk menyesuaikan kebijakan, terutama melalui penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Permendes No. 13 Tahun 2020. Desa Ongkaw 1, Kabupaten Minahasa Selatan, menjadi contoh bagaimana pemerintah desa berperan penting dalam menjaga kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan dihadapkan pada keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, serta lemahnya konsistensi pelaksanaan kebijakan (Roring et al., 2021, hlm. 2-3)
Permasalahan implementasi kebijakan publik di Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan kelangkaan regulasi, tetapi justru terletak pada lemahnya penerapan di lapangan. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik birokrasi. Dari hasil kajian berbagai penelitian, setidaknya terdapat beberapa isu krusial yang dapat dirumuskan sebagai masalah utama.
Pertama, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik masih rendah. Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diamanatkan melalui PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 baru dilaksanakan oleh sekitar 40,61% unit penyelenggara pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan partisipatif masih jauh dari harapan (Rachmat et al., 2023, hlm. 2-3)
Kedua, terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara perumusan dan implementasi kebijakan. Otonomi desa, misalnya, seharusnya memperkuat kemandirian dalam mengelola sumber daya lokal, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala kapasitas, keterbatasan sumber daya, serta konflik kepentingan antar aktor lokal (Gulo et al., 2024, hlm. 388-389)
Ketiga, faktor eksternal dan lemahnya kapasitas institusional turut menjadi penghambat. Dominasi lembaga internasional, duplikasi kelembagaan, serta maladministrasi mengakibatkan banyak kebijakan yang gagal diimplementasikan, menimbulkan pemborosan sumber daya, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Kristian, 2023, hlm. 88-89)
Keempat, ketimpangan akses dan kualitas kebijakan pendidikan masih menjadi persoalan fundamental. Rendahnya kualitas guru, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi pusat–daerah membuat kebijakan pendidikan belum mampu meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia (Wijaya et al., 2024, hlm. 7095-7096)
Kelima, implementasi keterbukaan informasi publik masih belum konsisten. Meskipun UU No. 14 Tahun 2008 mengamanatkan transparansi, praktik di lapangan justru menunjukkan lemahnya akuntabilitas pejabat publik, maraknya korupsi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Chairunnisa et al., 2023, hlm. 32-34)
Keenam, kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya masih jauh dari implementasi efektif. Tingginya pencemaran lingkungan dan pembangunan yang tidak terkendali mencerminkan lemahnya konsistensi kebijakan lingkungan (Tay & Rusmiwari, 2019, hlm. 218-219)
Ketujuh, penanganan krisis, seperti pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa kebijakan publik di tingkat desa belum sepenuhnya adaptif. Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan pandemi masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (Roring et al., 2021, hlm. 2-3)
Implementasi kebijakan publik di Indonesia dapat dilihat dari berbagai indikator statistik yang menggambarkan capaian, kendala, maupun dampaknya di lapangan. Data berikut menunjukkan permasalahan nyata pada sektor pelayanan publik, pendidikan, lingkungan, transparansi, dan penanganan krisis.
Pertama, dalam konteks pelayanan publik, hasil monitoring Kementerian PANRB menunjukkan bahwa hanya 40,61% unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagaimana diamanatkan PermenPANRB No. 16 Tahun 2017. Dari total tersebut, tercatat 38 instansi kementerian/lembaga dan 215 pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan FKP pada periode 2020–2022 (Rachmat et al., 2023, hlm. 2-3)
Kedua, dalam bidang ketenagakerjaan, kebijakan publik yang tidak tepat berdampak serius terhadap meningkatnya pengangguran. Pasca implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, tingkat pengangguran di Indonesia meningkat, khususnya di kalangan lulusan perguruan tinggi. Kondisi ini memunculkan fenomena “generasi sandwich”, yaitu kelompok muda yang terbebani kebutuhan ekonomi keluarga akibat minimnya lapangan kerja yang layak (Kristian, 2023, hlm. 89)
Ketiga, di sektor pendidikan, kualitas layanan masih belum merata. Salah satu indikatornya adalah rendahnya kualitas tenaga pengajar. Data nasional menunjukkan bahwa keterbatasan dana pendidikan, terutama di daerah, mengakibatkan rendahnya akses pada pelatihan guru, serta masih adanya ketidakselarasan kurikulum dengan tuntutan pasar kerja. Hal ini berimbas pada rendahnya daya saing lulusan Indonesia di tingkat global (Dwi et al., 2024, hlm. 7095-7096)
Keempat, keterbukaan informasi publik masih menghadapi tantangan. Hasil penelitian Chairunnisa, Habibi, dan Berthanila (2023) menunjukkan bahwa variabel isi kebijakan memiliki pengaruh dominan terhadap implementasi keterbukaan informasi dengan tingkat pengaruh 99%, sementara variabel konteks kebijakan memberikan pengaruh sebesar 84,83%. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas isi kebijakan lebih menentukan dibandingkan dengan faktor konteks kelembagaan dalam penerapan UU No. 14 Tahun 2008 (Chairunnisa et al., 2023, hlm. 32)
Kelima, dalam pembangunan berkelanjutan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pencemaran lingkungan di daerah perkotaan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur. Studi kasus di Desa Tlekung, Kota Batu, memperlihatkan adanya pro dan kontra masyarakat terhadap pembangunan. Faktor pendukung antara lain ketersediaan sumber daya alam dan SDM, sementara hambatannya meliputi cuaca tidak menentu, kurangnya wawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan (Tay & Rusmiwari, 2019, hlm. 218-219)
Keenam, pandemi Covid-19 menunjukkan keterbatasan pemerintah desa dalam penanganan krisis. Berdasarkan Permendes No. 13 Tahun 2020, minimal 30% Dana Desa dialokasikan untuk penanggulangan pandemi. Namun, di Desa Ongkaw 1, implementasi kebijakan ini menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, masih adanya kegiatan sosial dengan lebih dari 20 orang, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan (Roring et al., 2021, hlm. 2-3)
Fenomena aktual implementasi kebijakan publik di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan regulasi dengan praktik di lapangan. Dalam sektor pelayanan publik, Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diatur melalui PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 hanya dilaksanakan oleh 40,61% unit penyelenggara pelayanan publik, meliputi 38 kementerian/lembaga dan 215 pemerintah daerah. Kondisi ini memperlihatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik (Rachmat et al., 2023, hlm. 2-3)
Di bidang ketenagakerjaan, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan persoalan baru. Alih-alih menciptakan peluang kerja luas, kebijakan tersebut justru dikritik karena mendorong peningkatan angka pengangguran, terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Fenomena ini berimplikasi pada lahirnya generasi sandwich, yaitu kelompok usia produktif yang terbebani kebutuhan ekonomi keluarga akibat terbatasnya lapangan kerja yang layak (Kristian, 2023, hlm. 89)
Dalam sektor pendidikan, mutu layanan masih menghadapi tantangan serius. Rendahnya kualitas guru, keterbatasan dana pendidikan, dan ketidakselarasan kurikulum dengan tuntutan pasar kerja membuat kualitas lulusan Indonesia belum mampu bersaing di tingkat global (Dwi et al., 2024, hlm. 7095-7096)
Isu keterbukaan informasi publik juga menjadi sorotan. Berdasarkan penelitian, isi kebijakan keterbukaan informasi berpengaruh 99%, sedangkan konteks kebijakan berpengaruh sebesar 84,83% dalam implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik lebih ditentukan oleh kualitas substansi kebijakan dibanding faktor kontekstual kelembagaan (Chairunnisa et al., 2023, hlm. 32)
Namun, lemahnya transparansi pejabat publik dan maraknya praktik korupsi di tingkat daerah memperburuk krisis kepercayaan masyarakat.
Dalam isu lingkungan hidup, meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi pembangunan berkelanjutan masih lemah. Studi di Desa Tlekung, Kota Batu, memperlihatkan bahwa masyarakat terbelah antara pihak yang pro dan kontra pembangunan. Hambatan utama adalah cuaca yang tidak menentu, kurangnya wawasan, serta pola pikir masyarakat yang belum memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan (Tay & Rusmiwari, 2019, hlm. 218-219)
Sementara itu, pandemi Covid-19 menjadi ujian nyata bagi birokrasi desa. Permendes No. 13 Tahun 2020 mewajibkan alokasi minimal 30% Dana Desa untuk penanganan pandemi. Namun, di Desa Ongkaw 1, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, tetap adanya kegiatan masyarakat dengan lebih dari 20 orang, serta rendahnya kesadaran warga terhadap protokol kesehatan (Roring et al., 2021, hlm. 2-3)
Fenomena-fenomena aktual ini memperlihatkan bahwa problem utama kebijakan publik di Indonesia bukanlah ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya implementasi. Persoalan partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas tata kelola, serta inkonsistensi birokrasi menjadi tantangan yang harus segera dibenahi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sintesis :
Implementasi kebijakan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang membuat banyak kebijakan gagal mencapai tujuannya. Permasalahan utama bukan terletak pada kelangkaan regulasi, melainkan pada lemahnya penerapan di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik di sektor pelayanan publik, pendidikan, lingkungan, keterbukaan informasi, ketenagakerjaan, maupun penanganan krisis. Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi pusat-daerah, pengaruh eksternal, hingga praktik maladministrasi dan korupsi menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini berdampak pada pemborosan sumber daya, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta rendahnya kualitas pelayanan dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi kebijakan publik penting dilakukan untuk menemukan strategi perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Daftar Pustaka (ASA) :
Chairunnisa, Lathifah, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila. 2023. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.” Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) 11(2):31–45. doi:10.47828/jianaasian.v11i2.158.
Dwi, Fazza Erwina, Hafidz Maullana, Hariesty Octari Utami, and Hansein Arif Wijaya. 2024. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik.” JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 7(7):7094–7100.
Gulo, Titi Rawati, Rosalia Mendrofa, and Elazhari. 2024. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SERTA TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK BERDASARKAN TEORI ADMINISTRASI NEGARA SAAT INI.” Jurnal Genta Mulia 15(1):387–92.
Kristian, Indra. 2023. “Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia.” Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial 21(2):88–98. doi:10.63309/dialektika.v21i2.155.
Rachmat, Rachmat, Edy Sutrisno, and Mala Sondang Silitonga. 2023. “Strategi Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017).” Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik 5(2):1–10.
Roring, Andreas Delpiero, Michael Mantiri, and Marlien T. Lapian. 2021. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.” Governance 1(2):1–10.
Tay, Dicky Siswanto Renggi, and Sugeng Rusmiwari. 2019. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) 8(4):217–22. doi:10.33366/jisip.v8i4.1950.
download pdf disini
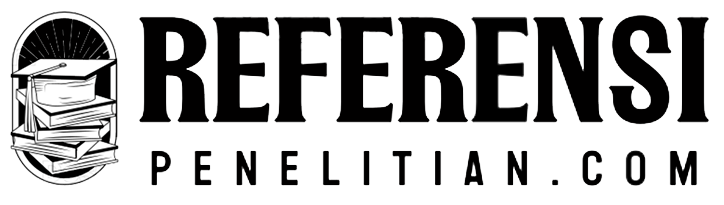

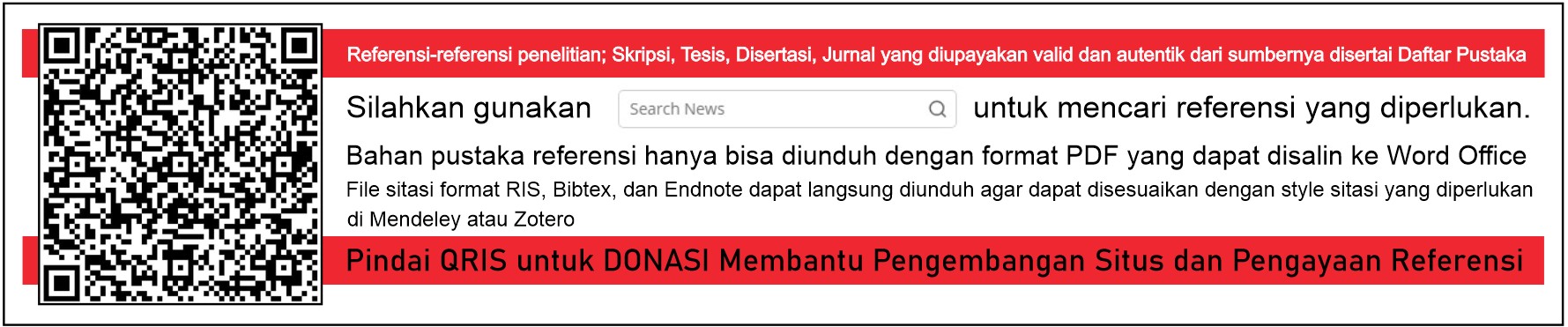
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.info/en-IN/register-person?ref=A80YTPZ1
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.info/pt-PT/register-person?ref=KDN7HDOR