Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam membangun peradaban manusia. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu, melainkan juga proses pembentukan akhlak, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Filsafat pendidikan Islam dengan demikian hadir sebagai dasar pemikiran yang menyatukan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (Ya’kub dkk., 2023: 163).
Pendidikan Islam sejak dahulu berperan dalam melahirkan generasi yang berilmu sekaligus berakhlak. Namun dalam realitasnya, implementasi pendidikan Islam menghadapi berbagai persoalan, baik dalam aspek metodologis, kelembagaan, maupun epistemologi keilmuan. Tantangan globalisasi, penetrasi sekularisme, serta persoalan internal seperti rendahnya mutu kurikulum dan ketimpangan kualitas guru, semakin mempertegas urgensi kajian filsafat pendidikan Islam (Ya’kub dkk., 2023: 169).
Konsep pendidikan dalam Islam bersifat komprehensif. Ia menekankan pengembangan manusia yang utuh: spiritual, intelektual, moral, dan sosial (Ya’kub dkk., 2023: 164). Pendidikan tidak hanya berhenti pada ranah kognitif, melainkan mencakup penguatan karakter dan orientasi hidup yang selaras dengan nilai-nilai Islam.
Namun demikian, implementasi pendidikan Islam menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah terjadinya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam proses pembelajaran (Burga, 2019). Selain itu, masih lemahnya kualitas tenaga pendidik dan rendahnya daya saing lulusan lembaga pendidikan Islam memperburuk problematika ini.
Di sisi lain, pendidikan Islam memiliki akar yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Sejak pra-kemerdekaan hingga kini, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, hingga sekolah umum berciri Islam telah menjadi bagian integral sistem pendidikan nasional (Ya’kub dkk., 2023: 170). Keberadaan lembaga ini membuktikan bahwa pendidikan Islam mampu bertahan dan berkembang meski dihadapkan pada berbagai tantangan modernitas.
Fenomena
Pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Agama RI (2022), tercatat lebih dari 82.418 madrasah formal dengan lebih dari 10,5 juta peserta didik; 30.400 pondok pesantren dengan santri lebih dari 5 juta orang; UIN/IAIN/STAIN dan PTKI swasta yang berjumlah lebih dari 800 institusi dengan mahasiswa lebih dari 1,2 juta.
Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan yang muncul adalah bagaimana menjaga mutu lulusan agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas keislamannya.
Kajian Teori
Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philos (cinta) dan sophia (kebijaksanaan), sehingga secara harfiah berarti “cinta terhadap kebijaksanaan”. Dalam konteks keilmuan, filsafat dimaknai sebagai dasar pemikiran yang mendalam terhadap hakikat pengetahuan dan kehidupan. Plato mendefinisikan filsafat sebagai “pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli”, sementara Aristoteles menyebutnya sebagai “ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, termasuk metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika”. Al-Farabi menyatakan bahwa filsafat adalah “pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu yang sebenarnya” (Ya’kub dkk., 2023: 166).
Dalam perspektif Islam, filsafat pendidikan merupakan penerapan prinsip filsafat dalam bidang pendidikan yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah. Al-Syaibany mendefinisikan filsafat pendidikan sebagai penerapan pandangan filosofis untuk menyelesaikan problematika pendidikan secara praktis. Artinya, filsafat pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga operasional dalam menjawab kebutuhan pendidikan umat (Ya’kub dkk., 2023: 167).
Pendidikan Islam didefinisikan sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam untuk membentuk pribadi utama sesuai ajaran Islam (syakhsiyyah islamiyyah). Marimba (1974) menjelaskan bahwa pendidikan Islam memiliki tiga unsur pokok:
- Mengembangkan potensi jasmani dan rohani.
- Berdasarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis.
- Bertujuan membentuk pribadi utama sesuai ukuran Islam (Ya’kub dkk., 2023: 167).
Syed Muhammad Naquib al-Attas menegaskan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah cara berpikir tentang pendidikan sebagai bagian integral dari pengembangan totalitas manusia, mencakup aspek spiritual, intelektual, moral, sosial, dan estetika. Sedangkan Ismail al-Faruqi menyebutnya sebagai usaha sadar manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang Tuhan, dirinya, alam semesta, serta mengembangkan kualitas diri dalam bingkai pandangan dunia Islam (Ya’kub dkk., 2023: 168).
Dengan demikian, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yakni manusia yang seimbang dalam iman, ilmu, dan amal.
Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam sangat luas, meliputi:
- Tujuan pendidikan
- Kurikulum
- Pendidik dan peserta didik
- Metode dan materi pembelajaran
- Evaluasi pendidikan
- Lingkungan pendidikan (Ya’kub dkk., 2023: 169).
Menurut Muhaimin (2002), ruang lingkup tersebut dapat dilihat dari dua dimensi utama:
- Dimensi lingkungan pendidikan, yang mencakup pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- Dimensi jenis permasalahan pendidikan, yang meliputi masalah landasan pendidikan, struktur kelembagaan, dan operasional pendidikan.
Ruang lingkup ini menegaskan bahwa filsafat pendidikan Islam bersifat sistemik, tidak hanya membahas hal teknis tetapi juga menyentuh aspek filosofis yang mendasarinya.
Perkembangan Filsafat Pendidikan Islam
Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam telah hadir sejak masa pra-kemerdekaan melalui pesantren, madrasah, dan surau. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan Islam semakin berkembang dengan hadirnya sekolah Islam modern, madrasah negeri/swasta, serta perguruan tinggi Islam (Ya’kub dkk., 2023: 170).
Namun, terdapat faktor eksternal yang menghambat perkembangan pendidikan Islam, seperti penetrasi orientalis, misionaris Kristen, serta pengaruh sekularisasi pendidikan dari Barat. Karena itu, ditegaskan bahwa filsafat pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah agar tetap relevan dan berakar pada identitas Islam (Ya’kub dkk., 2023: 171).
Filsafat Pendidikan Islam sebagai Ilmu: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi
- Ontologi
Ontologi filsafat pendidikan Islam berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk pedagogik, yakni makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Ia diciptakan Allah dengan fitrah yang memungkinkan berkembangnya potensi intelektual, spiritual, dan sosial. Pendidikan hadir untuk mengarahkan manusia agar mampu menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi (Ya’kub dkk., 2023: 171).
- Epistemologi
Epistemologi pendidikan Islam berbeda dengan Barat. Tradisi Barat cenderung mengedepankan skeptisisme, rasionalisme, positivisme, dan dikotomi antara ilmu dan nilai. Sebaliknya, epistemologi pendidikan Islam menempatkan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan, disertai akal dan pengalaman empiris. Dengan demikian, pengetahuan tidak sekadar imanen, tetapi juga transenden, mengantarkan manusia menuju pengakuan terhadap Allah (Qomar, 2005; Ya’kub dkk., 2023: 173).
- Aksiologi
Aksiologi pendidikan Islam menekankan nilai guna pendidikan. Pendidikan Islam harus membentuk manusia yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berorientasi pada tauhid. Keseimbangan antara ilmu, etika, dan estetika menjadi ciri khas aksiologi pendidikan Islam (Wardi, 2013 dalam Ya’kub dkk., 2023: 174).
Menurut Ya’kub dkk. (2023: 168), pendidikan Islam bertujuan membentuk karakter utama yang disebut Syakhsiyyah Islamiyyah. Karakter tersebut meliputi sepuluh indikator, di antaranya:
- Salimul Aqidah (aqidah lurus)
- Shahihul Ibadah (ibadah benar)
- Matinul Khuluq (akhlak kokoh)
- Qawwiyul Jismi (fisik kuat)
- Mushaqqaful Fikri (berpengetahuan luas)
- Qadirun Ala Kasbi (mandiri)
- Munazzamun fi Syu’unih (teratur)
- Harisun Ala Waqtihi (disiplin waktu)
- Nafi’un li Ghairihi (bermanfaat bagi orang lain)
- Mujahidun Linafsihi (berjuang melawan hawa nafsu)
Kesepuluh orientasi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bersifat komprehensif, menekankan keseimbangan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial.
Daftar Pustaka
Ya’kub, Bahaking Rama, & Muh. Natsir Mahmud. (2023). Filsafat Pendidikan dalam Perspektif Islam. Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 14(2), 163–175.
Arifin, H.M. (2017). Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Aziz, Abd. (2009). Filsafat Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras.
Burga, Muhammad Al-Qadri. (2019). Hakikat Manusia sebagai Makhluk Pedagogik. Jurnal Al-Musannif, 1(1), 19–31.
Mulkhan, Abdul Munir. (2002). Nalar Spiritual Pendidikan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Qomar. (2005). Epistemologi Pendidikan Islam. Jakarta: Erlangga.
Sadulloh, Uyoh. (2014). Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Tafsir, Ahmad. (2006). Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Wardi, Moh. (2013). Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya. Jurnal Tadris, 8(1), 65–67.
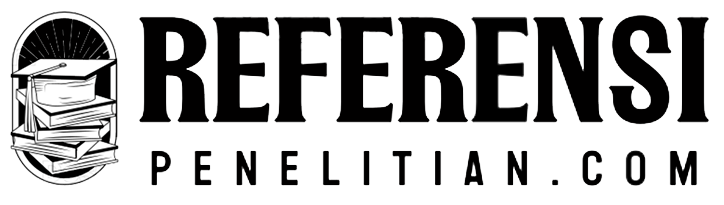

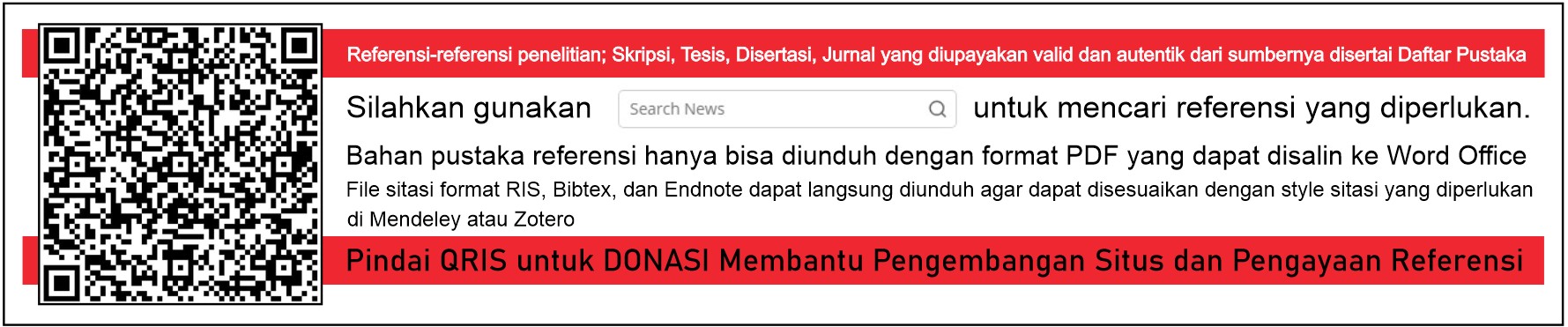
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://www.binance.com/register?ref=IHJUI7TF
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.info/en-NG/register?ref=YY80CKRN
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.